Oleh Sudarsono dan Hari Winarsa*
Sampah yang biasanya jadi masalah, di Pondok Pesantren Minhaajurroosyidiin justru diolah jadi betkah. Dari sisa limbah dapur yang berubah jadi pakan ikan hingga pupuk organik untuk pertanian perkotaan, pesantren ini membuktikan zero waste bisa nyata dan menguntungkan.
Indonesia menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan sampah. Dari plastik sekali pakai hingga limbah organik, jumlahnya terus meningkat dan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan serta kesehatan. Kondisi ini menegaskan pentingnya penerapan konsep zero waste sebagai strategi mengurangi sampah sejak dari sumbernya.
Bayangkan kalau gerakan ini diterapkan di pondok pesantren, yang bukan hanya tempat belajar agama, tapi juga pusat kehidupan sosial dan ekonomi. Ribuan santri tinggal, makan, dan belajar bareng di pondok pesantren—otomatis juga menghasilkan banyak sampah. Sebagai lembaga pendidikan berbasis komunitas dengan santri yang banyak dan jaringan yang luas, pondok pesantren juga memiliki peran strategis sebagai pusat sosial dan ekonomi serta dapat menjadi motor perubahan dan pionir gerakan lingkungan. Apalagi, dalam Islam sendiri ada nilai kuat soal menjaga kebersihan, hidup sederhana, dan tanggung jawab menjaga bumi.
Lebih keren lagi, kalau implementasi zero waste di pondok pesantren bisa dikaitkan dengan ekonomi sirkuler. Jadi, sampah di pondok pesantren bukan lagi dianggap masalah, tapi bisa jadi rupiah. Misalnya, biokonversi sampah dapur menjadi maggot buat pakan ikan dan pupuk organik/kompos buat kebun pesantren, atau sampah plastic anorganik dikreasikan jadi produk bernilai jual. Hasilnya? Lingkungan lebih bersih, pondok pesantren lebih mandiri, dan santri belajar langsung praktik hidup berkelanjutan.
Dengan mewujudkan ekonomi sirkuler, penerapan zero waste di pondok pesantren dapat sejalan dengan sustainable development goal no. 12 (SDG12: Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab). Opini ini menjawab pertanyaan: bagaimana implementasi zero waste dapat mewujudkan ekonomi sirkuler di pondok pesantren? dan mendeskripsikan strategi implementasi serta menunjukkan dampak ekonomi, sosial, ekologis, dan kontribusinya terhadap SDGs.
Ekonomi Sirkuler dan Zero Waste
Zero waste bukan sekadar tren gaya hidup ramah lingkungan, tapi sebuah filosofi tentang bagaimana manusia bisa hidup tanpa menghasilkan sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Jadi, bukan cuma soal buang sampah pada tempatnya, tapi lebih jauh: mengubah cara kita memandang barang dan limbah. Prinsip dasarnya sering disebut 5R: Refuse (menolak barang yang nggak perlu), Reduce (mengurangi penggunaan), Reuse (memakai ulang), Recycle (mendaur ulang), dan Rot (mengomposkan sampah organik). Konsep zero waste selaras dengan SDG12, yang menekankan konsumsi dan produksi berkelanjutan.
Ekonomi linear itu polanya “ambil–pakai–buang”, sedangkan ekonomi sirkuler justru berusaha menjaga nilai barang dan material selama mungkin. Barang yang sudah dipakai nggak langsung jadi sampah, tapi bisa masuk ke siklus baru: diperbaiki, diolah, atau diubah jadi produk lain. Dengan begitu, sumber daya alam bisa lebih hemat, dan limbah yang mencemari lingkungan bisa ditekan. Jadi, konsep zero waste nyambung banget dengan gagasan ekonomi sirkuler. Ekonomi sirkuler melengkapi konsep zero waste dengan menekankan siklus penggunaan sumber daya agar nilainya tetap terjaga dengan mendorong perbaikan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali. Implementasi ekonomi sirkuler mendukung SDG13: Climate Action, karena mengurangi emisi dari sampah, serta SDG 15: Life on Land, dengan menjaga ekosistem darat dari pencemaran.
Kalau ditarik ke konteks pesantren, landasan teorinya makin kuat. Dalam Islam, ada ajaran bahwa manusia adalah khalifah fil ardh—pemimpin di bumi yang punya tanggung jawab menjaga kelestarian alam. Ada juga nilai menjaga kebersihan dan kesucian yang jadi bagian penting dari ibadah sehari-hari. Dengan demikian, menjaga lingkungan bukan cuma urusan sosial, tapi juga bagian dari spiritualitas.
Pondok pesantren juga menjadi pusat pembentukan karakter dan gaya hidup santri dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya. Kalau santri sejak dini diajarkan prinsip zero waste dan ekonomi sirkuler, mereka bisa jadi agen perubahan di masyarakat. Berdasarkan teori ini, pesantren punya modal sosial, budaya, dan religius yang kuat untuk mengintegrasikan praktik ramah lingkungan ke dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan menggabungkan konsep zero waste, ekonomi sirkuler, dan nilai-nilai Islam, kita bisa melihat bahwa implementasinya di pondok pesantren bukan sekadar wacana, tapi punya dasar teoritis yang kokoh. Premis ini menjadi fondasi yang akan mengarahkan pembahasan selanjutnya: bagaimana teori ini bisa diwujudkan dalam praktik nyata di kehidupan pondok pesantren.
Konteks Pondok Pesantren
Kalau kita lihat lebih dekat, pondok pesantren punya posisi unik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bukan hanya tempat belajar agama, pesantren juga jadi pusat kehidupan sosial, budaya, bahkan ekonomi. Ribuan santri tinggal bersama dalam satu lingkungan, dengan aktivitas harian yang padat: belajar, makan, beribadah, hingga kegiatan sosial. Dari pola hidup komunal ini, otomatis muncul tantangan baru, salah satunya soal pengelolaan sampah. Bayangkan, dari dapur umum saja bisa terkumpul berton-ton sisa makanan setiap bulan, belum lagi plastik dari jajanan atau kebutuhan sehari-hari santri.
Namun, di balik tantangan itu, pesantren justru menyimpan potensi besar. Pertama, komunitasnya solid. Santri terbiasa hidup disiplin, mengikuti aturan, dan bergerak bersama. Artinya, kalau ada program zero waste, peluang untuk diterapkan secara konsisten sangat tinggi. Kedua, pesantren punya nilai religius yang kuat. Ajaran Islam tentang kebersihan, kesederhanaan, dan tanggung jawab menjaga bumi bisa jadi landasan moral yang mendorong perubahan perilaku. Ketiga, pesantren sering kali punya lahan pertanian atau peternakan kecil. Limbah organik bisa diolah jadi kompos atau pakan, yang kemudian kembali mendukung kemandirian pangan pesantren. Ketiga potensi tersebut bisa menjadi basis penerapan zero waste.
Selain itu, pesantren juga punya pengaruh luas ke masyarakat sekitar. Apa yang dipraktikkan di dalam pesantren biasanya ditiru oleh warga sekitarnya. Jadi, kalau pesantren berhasil menerapkan zero waste, dampaknya bisa menular ke lingkungan yang lebih luas. Dengan kata lain, pesantren juga bisa jadi laboratorium hidup untuk mewujudkan gaya hidup berkelanjutan. Praktik ramah lingkungan di pesantren mendukung pencapaian SDG 11: Sustainable Cities and Communities.
Implementasi Zero Waste di Pondok Pesantren
Implementasi zero waste di pondok pesantren bisa diwujudkan lewat langkah-langkah nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari santri. Kuncinya ada pada perubahan pola pikir dan kebiasaan, karena tanpa kesadaran kolektif, program sebesar apa pun akan sulit berjalan. Maka, tahap pertama adalah edukasi. Santri perlu diberi pemahaman bahwa sampah bukan sekadar sesuatu yang dibuang, melainkan sumber daya yang masih punya nilai. Edukasi ini bisa dilakukan lewat kajian tematik, diskusi rutin, atau bahkan praktik langsung di lapangan.
Langkah berikutnya adalah pengelolaan sampah organik. Di pesantren, dapur umum biasanya menghasilkan sisa makanan dalam jumlah besar. Daripada dibuang, sisa ini bisa diolah melalui biokonversi menjadi maggot BSF, menjadi kompos atau pupuk cair. Hasil penanganan limbah organik kemudian dipakai untuk pakan alternatif dalam budidaya ikan dan pupuk organik dalam budidaya sayuran atau buah-buahan secara urban farming.
Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik, kertas, atau botol bisa dikelola lewat sistem bank sampah. Santri diajak memilah sampah sejak awal, lalu sampah yang terkumpul bisa dijual ke pengepul atau diolah menjadi produk kreatif, misalnya tas dari plastik kemasan atau kerajinan dari botol bekas. Produk ini bukan hanya mengurangi sampah, tapi juga bisa dijual untuk menambah pemasukan.
Selain pengelolaan sampah, penting juga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Pesantren bisa membuat aturan sederhana: santri membawa tumbler sendiri, kantin tidak lagi menyediakan sedotan plastik, dan kantong belanja diganti dengan tas kain. Aturan kecil ini, kalau dijalankan bersama-sama, akan memberi dampak besar.
Implementasi zero waste juga bisa diintegrasikan ke dalam kurikulum dan melalui praktik kewirausahaan berbasis daur ulang, sehingga santri tidak hanya belajar teori, tapi juga langsung mempraktikkan gaya hidup berkelanjutan.
Yang tak kalah penting adalah melibatkan masyarakat sekitar. Pesantren bisa membuka program pelatihan pengelolaan sampah untuk warga desa, atau mengajak mereka ikut serta dalam bank sampah. Dengan cara ini, pesantren bukan hanya mengubah lingkungannya sendiri, tapi juga memberi inspirasi dan dampak positif bagi komunitas yang lebih luas.
Jadi, implementasi zero waste di pondok pesantren bisa berjalan lewat kombinasi edukasi, pengelolaan sampah organik dan anorganik, pengurangan plastik sekali pakai, integrasi kurikulum, serta kolaborasi dengan masyarakat. Jika semua ini dilakukan secara konsisten, pesantren bukan hanya berhasil mengurangi sampah, tapi juga mewujudkan ekonomi sirkuler yang mandiri, berdaya, dan berkelanjutan. Integrasi ke dalam kurikulum atau praktek kewirausahaan hijau, memperkuat pendidikan berkelanjutan, sejalan dengan SDG 4: Quality Education.
Ekonomi Sirkuler di Pondok Pesantren
Ekonomi sirkuler pada dasarnya adalah cara baru melihat sumber daya: bukan lagi pola “ambil–pakai–buang”, tapi “pakai–olah–pakai lagi”. Rantai nilai ekonomi sirkuler di pondok pesantren dapat dilihat dari bagaimana setiap jenis limbah dikelola agar tetap memiliki nilai guna. Di pondok pesantren, konsep ekonomi sirkuler bisa diterapkan dengan sangat nyata karena aktivitas sehari-hari santri menghasilkan banyak aliran material yang bisa dimasukkan kembali ke siklus produktif.
Limbah organik yang berasal dari dapur umum, seperti sisa makanan atau sayuran, tidak lagi dianggap sebagai sampah, melainkan diolah menjadi input bagi kegiatan ekonomi lainnya, seperti budidaya ikan dan urban farming, yang outputnya (i.e., ikan, sayuran dan buah-buahan) bisa dimanfaatkan oleh pondok pesantren sehingga tercipta siklus pangan yang mandiri dan berkelanjutan.
Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik atau kertas bisa masuk ke rantai ekonomi sirkuler lewat bank sampah. Santri belajar memilah, lalu sampah bernilai jual dikumpulkan dan dijual ke pengepul. Ada juga yang bisa diolah jadi produk kreatif, seperti tas dari plastik kemasan atau hiasan dari botol bekas. Produk ini bisa dipasarkan, sehingga melatih jiwa kewirausahaan santri.
Dampaknya tidak hanya ekonomi. Secara sosial, santri terbiasa hidup disiplin, peduli lingkungan, dan kreatif mencari solusi. Mereka bisa jadi agen perubahan di masyarakat, serta membawa praktik ekonomi sirkuler ke lingkungan sekitar. Secara ekologis, pesantren berkontribusi mengurangi sampah yang berakhir di TPA, sekaligus menekan emisi dari pembakaran sampah.
Dampak dari penerapan ekonomi sirkuler ini bersifat multidimensi. Dari sisi ekonomi, pesantren mampu mengurangi biaya operasional sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru. Dari sisi sosial, santri terbiasa hidup disiplin, peduli lingkungan, dan berperan sebagai agen perubahan di masyarakat. Dari sisi ekologis, jumlah sampah yang berakhir di TPA berkurang signifikan, sekaligus mendukung SDG 13: Climate Action dengan menekan dampak perubahan iklim. Dengan demikian, pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan agama, tetapi juga teladan nyata dalam mewujudkan kehidupan berkelanjutan.
Implementasi Ekonomi Sirkuler di Pondok Pesantren Minhaajurroosyidiin
Beberapa pesantren di Indonesia, termasuk Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin, Pondok Gede, Jakarta Timur, DKI Jakarta – sudah merintis dan mulai membuktikan bahwa konsep zero waste bukan sekadar teori, tapi bisa benar-benar dijalankan. Contoh nyata yang telah dipraktekkan oleh Pesantren Ekologi Ath-Thaariq di Garut, yang mengajak santri mengelola sampah organik dari dapur untuk dijadikan kompos. Pesantren An-Nur II di Malang yang mengembangkan bank sampah dan mengajak santri memilah sampah, lalu menukarkannya dengan nilai ekonomi. Pondok Pesantren Daarut Tauhid di Bandung yang mendorong gerakan pengurangan plastik sekali pakai dan mewajibkan membawa tumbler dan kantong kain – merupakan beberapa contoh nyata implementasi zero waste di pondok .
Di Pondok Pesantren Minhaajurroosyidiin, telah dikembangkan tiga subsistem untuk menangani sampah menuju pondok pesantren zero waste. Subsistem pertama: biokonversi sampah sisa makanan dan sisa dapur dengan maggot BSF, dan fermentasi sampah organik lainnya (dedaunan dan potongan rumput) menjadi silase dan pupuk organik. Subsistem kedua: budidaya ikan nila, lele dan belut secara intensif dengan sistem bioflok. Subsistem ketiga: budidaya sayuran dan buah-buahan menggunakan pendekatan pertanian perkotaan (urban farming).
Ketiga subsistem tersebut menjadi tulang punggung perwujudan ekonomi sirkuler di Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin. Sampah organik yang dihasilkan menjadi input biokonversi sampah menjadi maggot BSF dan pupuk organik, output maggot BSF menjadi input untuk sumber protein pakan alternatif ikan nila, lele dan belut (i.e. pengganti sumber protein pakan ikan dari tepung kedelai dan tepung ikan) serta input pupuk organik untuk urban farming sayuran dan buah, output limbah air dari budidaya ikan nila dan lele dimanfaatkan sebagai input untuk penyiraman dan pupuk cair bagi urban farming, selanjutnya output sisa-sisa limbah organik dari urban farming dimanfaatkan sebagai input untuk produksi pupuk organik, budidaya ikan, dan biokonversi sampah menjadi maggot BSF.
Yang paling utama output dari budidaya ikan nila, lele dan belut serta urban farming sayuran dan buah-buahan otomatis menjadi input memasok kebutuhan dapur dan bisa langsung dimanfaatkan untuk pondok pesantren. Dari praktek tersebut, semua output limbah organik pondok pesantren akan terkelola dan tertangani secara internal, tidak perlu diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA) dan bahkan memberikan nilai tambah berupa produk ikan dan sayuran yang bisa dimanfaatkan untuk pondok pesantren.
Implementasi penanganan limbah organik dengan tiga subsistem: Biokonversi dengan maggot BSF – Budidaya ikan nila, lele dan belut – urban farming, terbukti mampu menangani limbah organik dan menjadi perwujudan ekonomi sirkuler di lingkup Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin. Model penanganan limbah pondok pesantren untuk mewujudkan ekonomi sirkuler tersebut selanjutnya menjadi embrio yang dapat direplikasi di pondok pesantren lain dengan kondisi dan situasi sama seperti Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin.
Setelah penanganan limbah organik dapat diselesaikan, rencana pengembangan selanjutnya adalah penanganan limbah anorganik, sehingga betul-betul bisa terwujud zero waste di lingkup Pondok Pesantren Minhaajurroosyidiin. Kegiatan penanganan limbah anorganik menggunakan pendekatan 5R: Refuse (menolak barang yang nggak perlu), Reduce (mengurangi penggunaan), Reuse (memakai ulang), dan Recycle (mendaur ulang), menjadi Langkah lanjutan yang perlu dilakukan.
Jika limbah organik dan anorganik telah dapat tertangani serta mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi, berarti Pondok Pesantren Minhaajurrosyidiin dapat dikembangkan sebagai model pondok pesantren zero waste yang mampu secara nyata mewujudkan model ekonomi sirkuler sehingga dapat direplikasi ke stakeholder yang memerlukan.
Tantangan dan Solusi
Meskipun konsep zero waste di pondok pesantren terdengar ideal, praktiknya tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan dana dan fasilitas. Banyak pesantren masih berfokus pada kebutuhan dasar pendidikan, sehingga pengelolaan sampah sering dianggap bukan prioritas. Selain itu, kesadaran santri dan masyarakat sekitar juga masih beragam. Tidak semua orang terbiasa memilah sampah atau mengurangi plastik sekali pakai, sehingga butuh waktu untuk membangun budaya baru. Tantangan lain adalah keterbatasan teknologi tepat guna. Misalnya, pengolahan biogas atau kompos sering terkendala peralatan dan keterampilan teknis.
Namun, setiap tantangan selalu punya solusi. Dari sisi pendanaan, pesantren bisa menjalin kerja sama dengan pemerintah, NGO, akademisi atau swasta yang peduli lingkungan. Dukungan ini bisa berupa pelatihan, bantuan alat, atau program pendampingan. Untuk meningkatkan kesadaran, pendekatan berbasis nilai agama sangat efektif. Santri dan masyarakat akan lebih mudah menerima perubahan jika dikaitkan dengan ajaran Islam tentang kebersihan dan tanggung jawab menjaga bumi. Sementara itu, keterbatasan teknologi bisa diatasi dengan inovasi sederhana, seperti komposter manual atau bank sampah berbasis komunitas.
Dengan kombinasi dukungan eksternal, pendekatan religius, dan inovasi lokal, pesantren dapat mengatasi hambatan yang ada. Justru dari proses inilah lahir model zero waste yang realistis, berkelanjutan, dan bisa ditiru oleh komunitas lain. Dengan strategi ini, pesantren dapat mengatasi hambatan dan tetap berkontribusi pada SDGs.
Sebagai penutup, implementasi zero waste di pondok pesantren bukan hanya strategi pengelolaan sampah, tetapi juga jalan menuju ekonomi sirkuler yang berkelanjutan. Praktik ini mendukung berbagai SDGs: SDG 4 (Quality Education), SDG 7 (Clean Energy), SDG 8 (Economic Growth), SDG 11 (Sustainable Communities), SDG 12 (Responsible Consumption), dan SDG 13 (Climate Action). Praktik ini tidak hanya menekan biaya operasional, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dan memperkuat kemandirian pesantren.
Pesantren bukan hanya mendidik santri dalam ilmu agama, tetapi dapat juga menyiapkan generasi muda yang peduli lingkungan, mandiri secara ekonomi, dan siap berkontribusi pada agenda global. Lebih jauh, penerapan zero waste di pondok pesantren dapat menumbuhkan kesadaran ekologis di kalangan santri, membentuk karakter peduli lingkungan, dan menjadikan mereka agen perubahan di masyarakat.
Nilai-nilai Islam tentang kebersihan dan tanggung jawab menjaga bumi menjadi pondasi moral yang memperkuat gerakan ini. Dengan demikian, pesantren dapat menjadi model nyata bagaimana pendidikan, spiritualitas, dan inovasi lingkungan berpadu untuk menciptakan kehidupan yang lebih bersih, mandiri, dan berkelanjutan melalui implementasi zero waste sebagai perwujudan ekonomi sirkuler.
**) Sudarsono adalah Koordinator Bidang (Korbid) Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), Sumberdaya Alam, dan Lingkungan Hidup (LISDAL), Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII)*
*Hari Winarsa adalah Anggota, Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), Sumberdaya Alam, dan Lingkungan Hidup (LISDAL), Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII)*


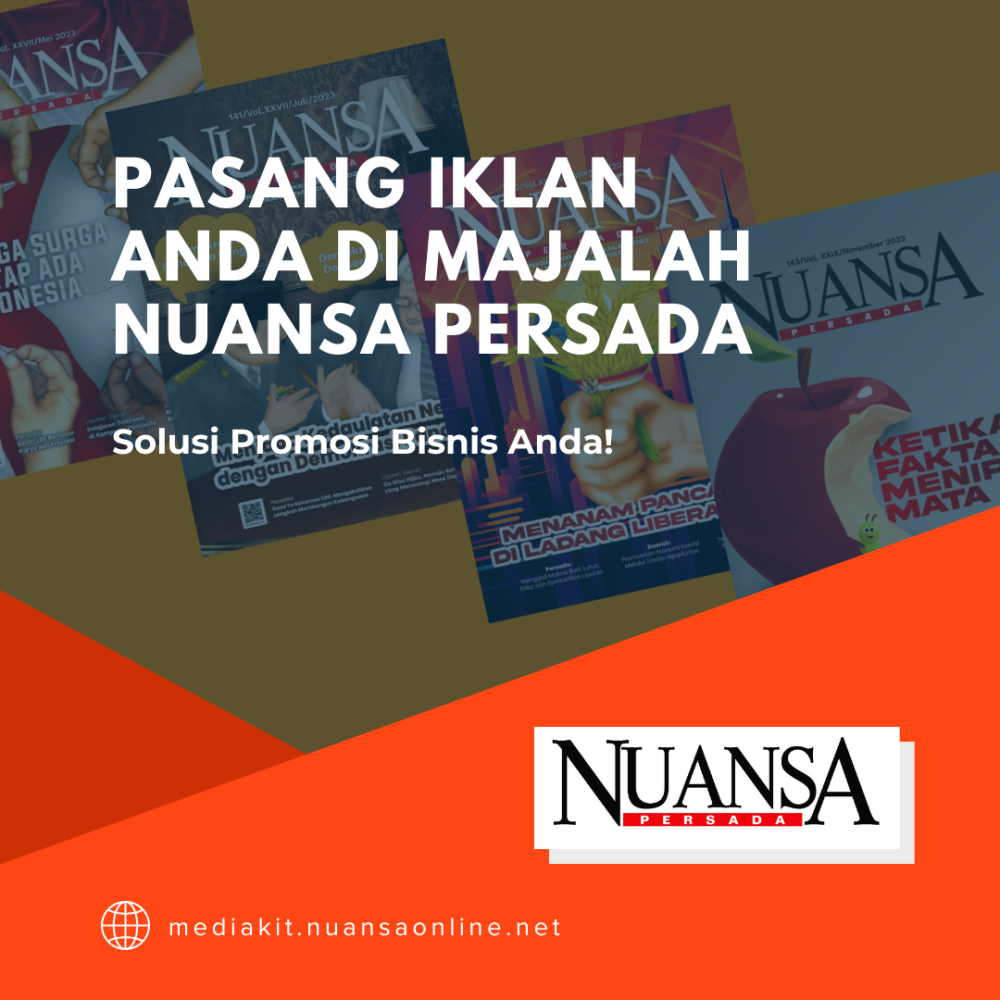










ALHAMDULILLAH SEMOGA MANFAAT DAN BAROKAH…..AAMIIN…..