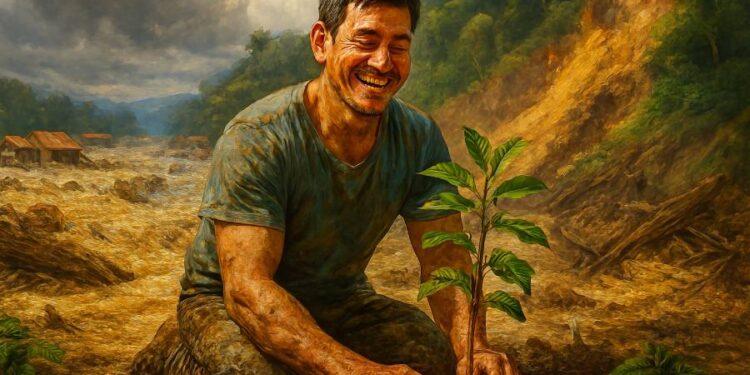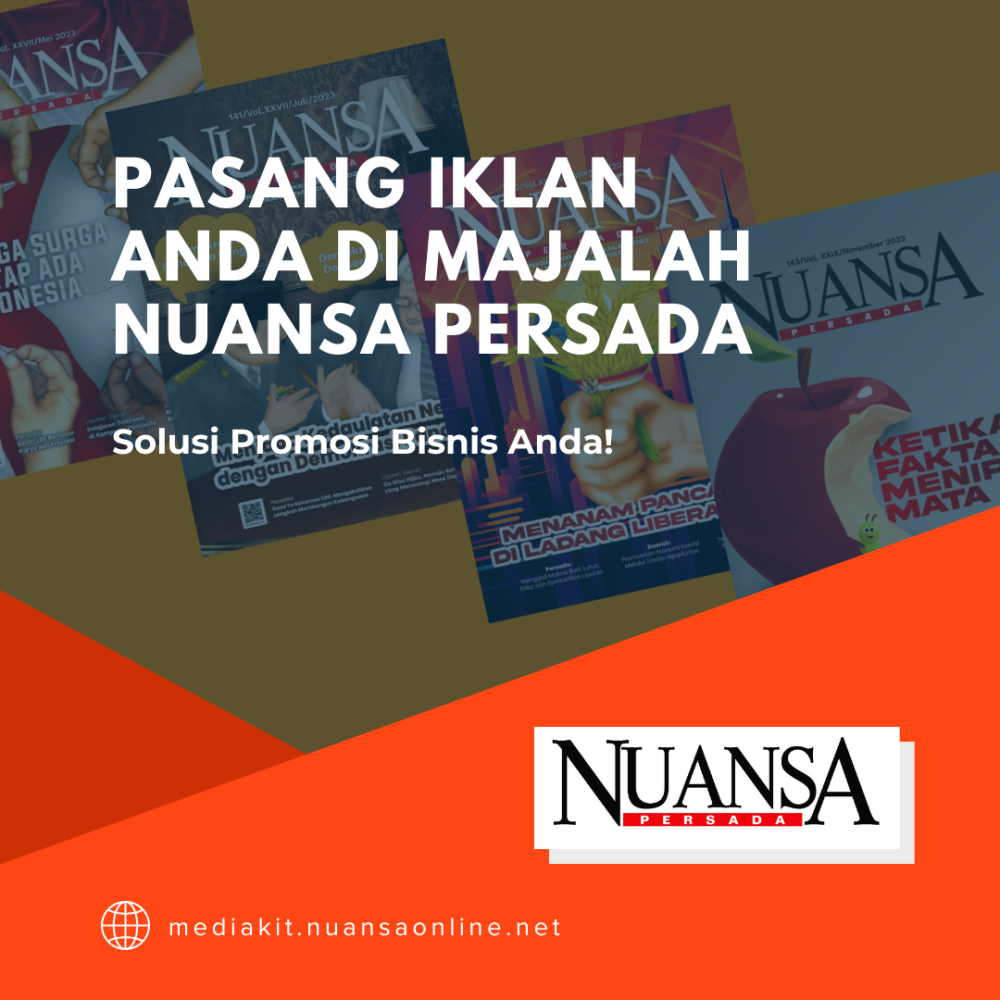Oleh Sudarsono dan Sri Wilarso*
“Indonesia yang dulu disebut paru-paru dunia, kini menghadapi kenyataan pahit: 12,7 juta hektare lahan kritis menunggu untuk dipulihkan. Hari Menanam Pohon Indonesia hadir setiap tahun, tetapi terlalu sering berhenti pada seremoni tanpa tindak lanjut nyata. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar menanam harapan untuk generasi mendatang, atau sekadar menanam krisis yang akan diwariskan?”
Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) yang diperingati setiap tanggal 28 November seharusnya bukan sekadar seremoni tahunan. Tema HMPI tahun ini adalah “Hijaukan Negeri, Pulihkan Bumi.” Kementerian Kehutanan RI akan memimpin Gerakan Penanaman Pohon Serentak di seluruh Indonesia. HMPI tahun ini harus menjadi momentum refleksi atas hubungan manusia dengan alam, sekaligus pengingat bahwa masa depan bangsa bergantung pada keberanian kita menjaga bumi.
Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia, dengan hutan tropis yang luas dan kaya biodiversitas. Namun, di balik kebanggaan itu, terdapat kenyataan pahit: jutaan hektare lahan kritis yang terus bertambah akibat deforestasi, alih fungsi lahan, kebakaran hutan, dan eksploitasi tambang. Data terbaru Kementerian Kehutanan (2025) mencatat bahwa lahan kritis di Indonesia mencapai 12,7 juta hektare dari total 120,5 juta hektare kawasan hutan. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan alarm keras, bahwa kita sedang kehilangan penopang kehidupan.
Kenyataan yang ada, Indonesia kini menghadapi kenyataan pahit terkait adanya 12,7 juta hektare lahan kritis menunggu untuk dipulihkan. Kondisi ini semakin nyata ketika banjir dan longsor melanda Sumatera Utara pada akhir November 2025, menewaskan 34 orang dan membuat 52 lainnya hilang. Di Aceh, bencana serupa meluas ke 20 kabupaten/kota hingga memaksa pemerintah menetapkan status tanggap darurat. Bahkan di Jawa Tengah, banjir di Kebumen merendam ribuan rumah. Semua ini menunjukkan bahwa menanam pohon bukan sekadar seremoni, melainkan kebutuhan mendesak untuk mencegah bencana.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius: merehabilitasi 12 juta hektare lahan kritis sebagai bagian dari komitmen Forestry and Other Land Uses (FOLU) Net Sink 2030. Target ini disampaikan dalam Konferensi Perubahan Iklim ke-30 (COP30) di Brasil, dengan harapan sektor kehutanan menjadi penyerap emisi bersih pada tahun 2030. Namun, target besar ini tidak akan tercapai jika Hari Menanam Pohon hanya berhenti pada seremoni.
Pohon sebagai Penopang Kehidupan
Fungsi ekologis. Pohon adalah mesin kehidupan. Ia menyerap karbon dioksida, menghasilkan oksigen, menjaga siklus air, dan menahan tanah agar tidak longsor. Tanpa pohon, banjir dan kekeringan menjadi bencana rutin. Pohon juga menjadi rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna, menjaga keseimbangan ekosistem yang menopang kehidupan manusia.
Fungsi sosial-ekonomi. Lebih dari sekadar ekologi, pohon adalah sumber ekonomi. Buah, kayu, obat, hingga energi biomassa berasal dari pohon. Sengon, jati, dan mahoni menjadi komoditas kayu; mangga, durian, dan rambutan memberi pangan; sementara pohon herbal seperti sirih dan mahkota dewa memberi manfaat kesehatan. Pohon juga membuka peluang ekowisata: hutan kota, taman wisata alam, hingga jalur trekking yang menarik wisatawan.
Fungsi budaya dan spiritual. Dalam tradisi Nusantara, pohon bukan sekadar benda hidup, melainkan simbol kehidupan. Pohon beringin misalnya, menjadi lambang kekuatan dan perlindungan. Masyarakat adat di Kalimantan dan Papua memiliki ritual khusus untuk menanam dan menjaga pohon, sebagai bagian dari kosmologi mereka. Menanam pohon berarti menjaga hubungan spiritual dengan alam.
Tantangan Nyata dalam Penanaman Pohon
Degradasi lahan tidak hanya menurunkan kualitas ekosistem, tetapi juga memperparah bencana hidrometeorologi. Catatan BNPB menunjukkan bahwa sepanjang awal 2025 saja, sudah terjadi 298 bencana banjir dan longsor di berbagai daerah. Kasus di Sumatera Utara dan Aceh menjadi bukti nyata bahwa tanpa pohon yang menahan air dan tanah, hujan ekstrem berubah menjadi tragedi. Pohon yang hilang berarti perlindungan yang hilang.
Kerusakan lahan kritis. Alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit, tambang, dan permukiman telah merusak jutaan hektare lahan. Kebakaran hutan di lahan gambut memperparah kondisi. Tanah kehilangan kesuburan, air menghilang, dan pohon sulit tumbuh kembali.
Partisipasi masyarakat. Kesadaran masyarakat masih rendah. Banyak yang melihat pohon sebagai penghalang pembangunan, bukan penopang kehidupan. Konflik kepentingan muncul: masyarakat ingin hasil ekonomi cepat, sementara konservasi memberi hasil jangka panjang.
Keberlanjutan perawatan. Penanaman massal sering gagal karena tidak ada perawatan pasca tanam. Bibit ditanam, difoto, lalu dibiarkan mati. Tanpa penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama, pohon tidak akan bertahan.
Kebijakan dan koordinasi. Meski pemerintah telah menetapkan Peta Lahan Kritis Nasional melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 406 Tahun 2025, koordinasi antar lembaga sering lemah. Program berjalan parsial, tidak terintegrasi dengan sektor lain seperti pertanian, energi, dan tata ruang.
Di beberapa daerah, penanaman massal untuk penghijauan gagal karena salah pilih jenis pohon. Pohon yang ditanam tidak sesuai dengan kondisi tanah dan iklim, sehingga mati dalam hitungan bulan.
Strategi dan Solusi
Pemilihan jenis pohon sesuai lokasi. Rehabilitasi lahan kritis tidak bisa dilakukan secara seragam. Setiap daerah memiliki karakteristik unik yang membutuhkan strategi berbeda:
- Jawa Barat (hulu DAS Citarum, Ciliwung): puspa (Schima wallichii), damar (Agathis dammara), rasamala (Altingia excelsa) untuk menahan longsor dan menjaga sumber air.
- Sumatra Selatan dan Riau (lahan gambut): jelutung (Dyera polyphylla), meranti rawa (Shorea spp.), gelam (Melaleuca cajuputi) untuk memulihkan gambut.
- Kalimantan Timur dan Tengah (bekas tambang): sengon (Paraserianthes falcataria), ulin (Eusideroxylon zwageri), merbau (Intsia bijuga) untuk revegetasi dan nilai ekonomi.
- Sulawesi Tengah (rawan longsor): damar, beringin (Ficus benjamina), alpukat (Persea americana) untuk menahan tanah sekaligus memberi hasil buah.
- Papua dan Papua Barat (pesisir dan mangrove): mangrove (Rhizophora mucronata, Avicennia marina), sagu (Metroxylon sagu), ketapang (Terminalia catappa) untuk melindungi pesisir dan mendukung pangan lokal.
Teknik penanaman dan perawatan pascatanam. Penanaman harus dilakukan dengan persiapan lahan yang baik: lubang tanam sesuai akar, pupuk organik, dan penanaman di musim hujan. Perawatan pasca tanam mencakup penyiraman rutin, pemupukan tambahan, penyiangan gulma, pemasangan ajir, pengendalian hama, dan pemangkasan ringan. Monitoring pertumbuhan harus dilakukan secara berkala.
Kolaborasi multi pihak Keberhasilan menanam pohon membutuhkan kolaborasi. Pemerintah menyediakan kebijakan dan anggaran, swasta melalui CSR, akademisi dengan riset, dan masyarakat dengan partisipasi aktif. Skema kredit karbon bisa menjadi insentif bagi perusahaan untuk menanam pohon.
Insentif ekonomi hijau. Menanam pohon harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Ekowisata, hasil hutan bukan kayu, dan perdagangan karbon bisa menjadi sumber ekonomi hijau. Dengan insentif ini, masyarakat akan terdorong menjaga pohon.
Best practices internasional, Korea Selatan berhasil melakukan reforestasi besar-besaran setelah perang, menjadikan hutan kembali hijau. India memiliki program penanaman pohon massal dengan melibatkan jutaan warga. Brasil mengembangkan sistem agroforestri yang menggabungkan pohon dengan pertanian. Indonesia bisa belajar dari praktik-praktik ini.
Refleksi dan Ajakan Moral
Ketika melihat berita tentang banjir bandang di Sumatera Utara dan longsor di Aceh, semakin yakin bahwa menanam pohon adalah tindakan pencegahan paling sederhana namun paling efektif. Pohon bukan hanya memberi oksigen, tetapi juga menahan tanah, menyerap air, dan melindungi manusia dari bencana. Menanam pohon berarti menanam perlindungan.”
Menanam pohon adalah tindakan sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Alangkah indahnya, membayangkan ketika warga bersama-sama menanam pohon di bantaran sungai. Dan beberapa tahun kemudian, pohon itu tumbuh besar, akar menahan tanah, banjir berkurang, dan udara lebih sejuk. Pohon kecil yang dulu ditanam berubah menjadi pohon besar penopang kehidupan. Apalagi jika dapat merealisasikannya, tentulah akan menjadi jauh lebih indah.
Hari Menanam Pohon Indonesia harus menjadi ajakan moral: “menanam pohon adalah investasi untuk generasi mendatang.” Pohon yang kita tanam hari ini akan memberi oksigen, air, dan kehidupan bagi anak cucu kita.
Harapan masa depan bersama adalah Indonesia hijau, sehat, dan berkelanjutan. Pohon bukan sekadar simbol, melainkan peradaban. Menanam pohon berarti menanam harapan. Harapan untuk mewujudkan Indonesia hijau, sehat, dan berkelanjutan untuk anak cucu kita.
Penutup
Hari Menanam Pohon Indonesia tidak boleh berhenti pada seremoni. Ia harus menjadi gerakan berkelanjutan, karena setiap pohon yang ditanam adalah benteng harapan untuk melawan banjir dan longsor. Tanpa pohon, hujan ekstrem akan terus berubah menjadi tragedi. Dengan pohon, kita menanam harapan sekaligus perlindungan.
Pohon yang kita tanam adalah harapan yang kita rawat. Sukses penanaman pohon perlu strategi berbasis lokasi, kolaborasi multi pihak, dan partisipasi masyarakat. Jika kita gagal, yang kita tanam bukan pohon, melainkan krisis.
**) Prof. Dr. Ir. Sudarsono, M.Sc adalah Koordinator Bidang (Korbid) Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), Sumberdaya Alam, dan Lingkungan Hidup (LISDAL), Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII)*
**) Prof. Dr. Ir. Sri Wilarso Budi R, MS, adalah Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), Sumberdaya Alam, dan Lingkungan Hidup (LISDAL), Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII)*