Oleh Rubiyo dan Sudarsono*
Jangan cuma bangga tanah surga, kalau nanti generasi kita cuma bisa antre beras. Kaya sumber daya, tapi bisa krisis pangan. Mau jadi generasi yang sadar atau generasi yang kelaparan?
Ada sebuah adagium kuno yang berbunyi: “Generasi yang tidak mendidik dan menyiapkan orang-orang muda generasi berikutnya, maka generasi penerus mendatang akan menemui kesulitan dalam kehidupannya.”
Ungkapan ini bukan sekadar kata-kata indah, melainkan peringatan keras yang berlaku lintas ruang dan waktu. Dalam lingkup keluarga, adagium ini terbukti benar: orang tua yang gagal menanamkan nilai, keterampilan, dan bekal hidup kepada anak-anaknya, akan menyaksikan generasi berikutnya hidup dalam keterbatasan, kebingungan, bahkan keterpurukan. Dalam skala bangsa, dampaknya jauh lebih besar: sebuah negara yang lalai menyiapkan generasi penerusnya akan menghadapi krisis multidimensi—ekonomi, sosial, politik, dan terutama pangan.
Bangsa Indonesia, dengan segala kekayaan alam dan potensi manusianya, seharusnya menjadi contoh dalam menyiapkan kehidupan generasi mendatang. Namun, kenyataannya, kesadaran kolektif untuk mendidik dan menyiapkan generasi penerus secara sistematis dan berkelanjutan masih sangat minim. Kita sering terjebak pada urusan jangka pendek, sementara masa depan yang seharusnya kita rancang bersama justru terabaikan.
Belajar dari Amerika dan Kearifan Lokal Nusantara
Negara-negara maju seperti Amerika Serikat telah menunjukkan komitmen jangka panjang dalam mendidik warganya dan menjaga kelestarian sumber daya alamnya. Mereka tidak hanya berpikir untuk satu atau dua generasi, tetapi merancang kebijakan yang berdampak hingga puluhan generasi ke depan. Konsep sustainability (keberlanjutan) menjadi bagian integral dari kebijakan publik, riset ilmiah, hingga gaya hidup masyarakat.
Menariknya, sebagian dari prinsip keberlanjutan yang mereka terapkan justru terinspirasi dari kearifan lokal bangsa-bangsa agraris, termasuk Nusantara. Dalam budaya Jawa, Sunda, Minangkabau, Dayak, hingga Maluku, terdapat falsafah yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam demi anak cucu. Bahkan, ada nasihat kuno yang menyebutkan bahwa setiap keputusan harus mempertimbangkan dampaknya hingga tujuh generasi ke depan.
Lebih ironisnya lagi, justru bangsa yang menjadi sumber inspirasi malah belum sepenuhnya menerapkan prinsip tersebut dalam kehidupan bernegara. Indonesia belum memiliki agenda nasional yang secara eksplisit menyiapkan kehidupan untuk 2–7 turunan, apalagi 27 turunan ke depan. Yang ada baru sebatas jargon “pembangunan berkelanjutan,” namun implementasinya sering kali berhenti pada tataran dokumen, bukan tindakan nyata.
Ketahanan Pangan: Pilar Utama Keberlanjutan Bangsa
Ketahanan pangan adalah fondasi utama dalam menyiapkan kehidupan generasi mendatang. Tanpa pangan yang cukup, sehat, dan berkelanjutan, semua aspek pembangunan akan rapuh. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, bahkan stabilitas sosial dan politik sangat bergantung pada ketersediaan pangan.
Jika kita melihat proyeksi ke depan, terdapat sebuah realitas yang sangat mengkhawatirkan. Satu generasi manusia rata-rata berlangsung selama 25 tahun. Artinya, dalam rentang tiga hingga lima generasi—sekitar 75 hingga 125 tahun ke depan—kita akan menghadapi tantangan besar yang tidak bisa diabaikan. Pada tahun 2100, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 575 juta jiwa. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan gambaran nyata tentang betapa besar kebutuhan pangan yang harus dipenuhi.
Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, Indonesia diperkirakan memerlukan 35 juta hektar lahan pertanian aktif. Namun, kenyataan saat ini menunjukkan bahwa kita hanya memiliki sekitar 14–15 juta hektar lahan basah dan kering di luar perkebunan. Dengan demikian, terdapat kekurangan sekitar 20 juta hektar lahan yang harus dicari, disiapkan, atau dikelola secara lebih efisien.
Kondisi ini menegaskan bahwa tanpa perencanaan matang, bangsa kita akan menghadapi krisis pangan serius. Kekurangan lahan bukan hanya soal ketersediaan tanah, tetapi juga menyangkut tata kelola, kebijakan agraria, dan kesadaran kolektif. Jika tidak diantisipasi sejak sekarang, generasi mendatang akan menanggung beban berat akibat kelalaian kita hari ini.
Pertanyaannya “Adakah yang memikirkan hal ini secara serius?” Mungkin hanya segelintir ilmuwan dan akademisi yang tidak memiliki kepentingan pribadi, yang benar-benar memikirkan keberlanjutan kehidupan bangsa Indonesia. Sementara itu, sebagian besar masyarakat masih terbuai oleh narasi bahwa Indonesia adalah negara paling kaya di dunia, sehingga tidak pernah timbul kekhawatiran akan kekurangan sumber daya.
Narasi Kekayaan Sumber Daya Alam yang Meninabobokan
Sejak kecil, kita dibesarkan dengan keyakinan bahwa Indonesia adalah negeri yang “gemah ripah loh jinawi.” Lagu legendaris Koes Plus, Kolam Susu, menjadi simbol harapan pasif:
“Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman…”
Syair ini memang indah, tetapi jika hanya menjadi penghibur tanpa diiringi kesadaran dan tindakan nyata, maka ia berubah menjadi candu. Kita menjadi bangsa yang terlena, tidak waspada, dan tidak siap menghadapi tantangan masa depan.
Padahal, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa lahan pertanian semakin menyusut, kualitas tanah menurun, air bersih semakin langka, dan perubahan iklim mengancam stabilitas produksi pangan. Jika kita terus berpegang pada mitos kekayaan tanpa pengelolaan, maka kita sedang menggali lubang bagi generasi mendatang.
Tantangan Keterbatasan Lahan dan Produksi Pangan
Salah satu tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia di masa depan adalah keterbatasan lahan untuk memenuhi kebutuhan pangan. Berdasarkan proyeksi, pada tahun 2100 jumlah penduduk Indonesia dapat mencapai sekitar 575 juta jiwa. Angka ini berarti kebutuhan pangan akan meningkat secara drastis. Untuk mencukupi kebutuhan tersebut, Indonesia diperkirakan memerlukan 35 juta hektar lahan pangan aktif. Namun, saat ini lahan yang tersedia hanya sekitar 14–15 juta hektar, sehingga terdapat kekurangan lebih dari 20 juta hektar. Kekurangan ini bukan sekadar angka, melainkan ancaman nyata bagi ketahanan pangan bangsa.
Selain ketersediaan lahan, sistem produksi pangan juga harus ditingkatkan. Kita membutuhkan sistem produksi yang efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Pertanian tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola tradisional atau eksploitasi berlebihan, melainkan harus bertransformasi dengan teknologi modern yang adaptif terhadap perubahan iklim. Kebijakan agraria yang berpihak pada petani juga menjadi kunci, agar lahan pertanian tidak terus-menerus tergerus oleh kepentingan industri dan properti.
Namun, tantangan yang dihadapi sangat besar. Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri, perumahan, dan infrastruktur terus terjadi tanpa kendali. Di sisi lain, ketergantungan pada impor pangan membuat kedaulatan pangan semakin rapuh. Regenerasi petani juga menjadi masalah serius; semakin sedikit anak muda yang mau terjun ke dunia pertanian karena dianggap tidak menjanjikan. Padahal, tanpa petani muda, masa depan pangan bangsa akan terancam.
Tantangan lain adalah rendahnya insentif bagi pertanian berkelanjutan. Petani yang berusaha menjaga tanah dan lingkungan sering kali tidak mendapatkan dukungan yang memadai. Tata kelola air dan irigasi pun masih lemah, padahal air adalah faktor vital dalam produksi pangan. Ditambah lagi, penggunaan pupuk kimia berlebihan telah menyebabkan degradasi tanah, menurunkan kesuburan, dan mengancam produktivitas jangka panjang.
Semua tantangan ini menunjukkan bahwa persoalan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga soal tata kelola, kebijakan, dan kesadaran kolektif. Jika tidak segera diatasi, keterbatasan lahan dan lemahnya sistem produksi akan menjadi bom waktu bagi bangsa. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang menyeluruh: melindungi lahan pertanian, memperkuat kebijakan agraria, mendorong regenerasi petani, serta mengembangkan teknologi ramah lingkungan. Hanya dengan cara itu, Indonesia dapat memastikan ketersediaan pangan bagi ratusan juta penduduknya hingga generasi mendatang.

Solusi Strategis: Dari Wacana ke Aksi Nyata
Menjadikan wacana menjadi aksi nyata perlu Langkah-langkah strategis yang komprehensif dan berkelanjutan, serta melibatkan multi stake holder. Berikut adalah lima langkah strategis yang diusulkan untuk ditindaklanjuti.
1. Revolusi Pendidikan Pangan
Revolusi pendidikan pangan adalah langkah mendasar untuk menyiapkan generasi yang sadar akan pentingnya pangan sebagai fondasi kehidupan bangsa. Literasi pangan harus diintegrasikan ke dalam kurikulum nasional, tidak hanya dalam bentuk teori, tetapi juga praktik nyata seperti kebun sekolah, sehingga anak-anak dapat merasakan langsung proses menanam, merawat, dan memanen. Mereka perlu memahami siklus tanah, air, dan benih, serta menyadari bahwa setiap pilihan konsumsi memiliki dampak ekologis dan moral.
Dengan begitu, makan tidak lagi dipandang sekadar kebutuhan biologis, melainkan tindakan yang berhubungan dengan kelestarian alam dan tanggung jawab sosial. Revolusi ini juga menuntut keterlibatan keluarga sebagai laboratorium pertama, media massa sebagai penggerak kesadaran, serta perguruan tinggi sebagai pusat inovasi pangan berkelanjutan. Jika dijalankan secara konsisten, pendidikan pangan akan melahirkan generasi yang peduli lingkungan, menghargai kerja petani, dan mampu menjaga ketahanan pangan lintas generasi.
2. Peta Jalan Lahan Pangan Nasional
Peta jalan lahan pangan nasional merupakan langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pangan jangka panjang. Tahap pertama adalah melakukan identifikasi lahan tidur, lahan marginal, serta potensi konversi lahan non-produktif agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Banyak lahan di Indonesia yang terbengkalai atau dialihfungsikan tanpa perencanaan matang, padahal jika dikelola dengan teknologi tepat guna, lahan tersebut mampu menopang produksi pangan.
Selanjutnya, negara perlu membangun kebijakan alokasi lahan yang berpihak pada pangan, bukan hanya untuk kepentingan industri atau properti. Prioritas ini penting agar kebutuhan dasar rakyat tidak dikorbankan demi keuntungan jangka pendek. Terakhir, pelibatan masyarakat menjadi kunci. Transparansi dalam pengawasan dan pemanfaatan lahan akan mencegah penyalahgunaan serta menumbuhkan rasa memiliki. Dengan peta jalan yang jelas, Indonesia dapat memastikan setiap jengkal tanah berkontribusi pada ketahanan pangan lintas generasi.
3. Insentif untuk Produksi Berkelanjutan
Mendorong produksi pangan berkelanjutan tidak cukup hanya dengan wacana, tetapi harus diwujudkan melalui insentif nyata bagi para pelaku pertanian. Petani yang menerapkan prinsip agroekologi dan pertanian regeneratif layak mendapatkan penghargaan serta subsidi khusus, karena mereka bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati, dan keseimbangan ekosistem.
Selain itu, negara perlu mendorong investasi jangka panjang dalam teknologi pertanian ramah lingkungan, seperti sistem irigasi hemat air, pupuk organik, energi terbarukan, dan digitalisasi pertanian. Teknologi ini akan meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
Tidak kalah penting, harus dibangun ekosistem pasar yang mendukung produk lokal dan berkelanjutan, sehingga petani memperoleh harga yang adil dan konsumen memiliki akses pada pangan sehat. Dengan kombinasi insentif, investasi, dan pasar yang berpihak, produksi berkelanjutan dapat menjadi arus utama, bukan sekadar pilihan alternatif.
4. Gerakan Keluarga 7 Turunan
Gerakan Keluarga 7 Turunan adalah sebuah inisiatif yang menekankan pentingnya menyiapkan pangan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi mendatang. Melalui kampanye nasional “Siapkan Pangan untuk 7 Turunan”, masyarakat diajak untuk berpikir jauh ke depan, menanamkan kesadaran bahwa setiap keputusan dalam mengelola pangan akan berdampak pada anak cucu kita.
Keluarga menjadi garda terdepan dengan langkah sederhana namun bermakna: menanam tanaman pangan di pekarangan, menyimpan benih lokal sebagai warisan genetik, serta membangun kebun pangan mandiri yang dapat menopang kebutuhan sehari-hari. Lebih dari itu, gerakan ini mendorong agar ketahanan pangan menjadi bagian dari budaya keluarga dan komunitas, bukan sekadar aktivitas ekonomi. Dengan menjadikan pangan sebagai nilai hidup bersama, kita menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif, memperkuat solidaritas sosial, dan memastikan keberlanjutan pangan lintas generasi. Inilah warisan sejati bagi bangsa: kemandirian dan ketahanan pangan yang berakar dari keluarga.
5. Reformasi Kebijakan dan Tata Kelola
Reformasi kebijakan dan tata kelola pangan merupakan langkah mendasar untuk memastikan keberlanjutan pangan lintas generasi. Langkah pertama adalah evaluasi ulang terhadap UU Pangan, UU Pertanian, dan UU Agraria, agar seluruh regulasi berpihak pada prinsip keberlanjutan, bukan sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Regulasi yang ada perlu diselaraskan sehingga mampu melindungi lahan pertanian, menjamin hak petani, serta menjaga keseimbangan ekologi.
Selanjutnya, perlu dibentuk badan khusus lintas kementerian yang berfungsi merancang dan mengawal kebijakan pangan jangka panjang. Badan ini harus bekerja secara terintegrasi, tidak terjebak dalam ego sektoral, dan memiliki visi lintas generasi.
Yang tak kalah penting, proses perumusan kebijakan harus melibatkan akademisi, petani, tokoh adat, dan masyarakat sipil, sehingga keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat sekaligus kearifan lokal. Dengan tata kelola yang inklusif dan berorientasi masa depan, ketahanan pangan bangsa dapat terjaga secara berkelanjutan.
Seruan Moral dan Spiritual: Mari Bangkit Bersama
Menyiapkan pangan untuk generasi penerus bukan hanya tugas teknis, tetapi panggilan moral dan spiritual. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjadi khalifah di muka bumi—penjaga, bukan perusak. Dalam budaya lokal, kita mengenal prinsip “Tri Hita Karana” dan “Tata Tentrem Kerta Raharja” yang menekankan harmoni antara manusia, alam, dan Tuhan. Jika kita gagal menyiapkan kehidupan yang layak bagi anak cucu kita, maka kita telah mengkhianati amanah sejarah dan spiritualitas kita sebagai bangsa. Mari kita pikirkan dan kita sadarkan bangsa kita untuk menyiapkan masa depan kehidupan yang lebih baik.
*) Prof. Dr. Rubiyo, M.Sc, Peneliti Utama Bidang Pemuliaan dan Genetika Tanaman
*) Prof. Dr. Ir. Sudarsono, M.Sc, Kepala Bidang Bioteknologi Tanaman dan Koordinator Lab. Biologi Molekuler Tumbuhan, Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor


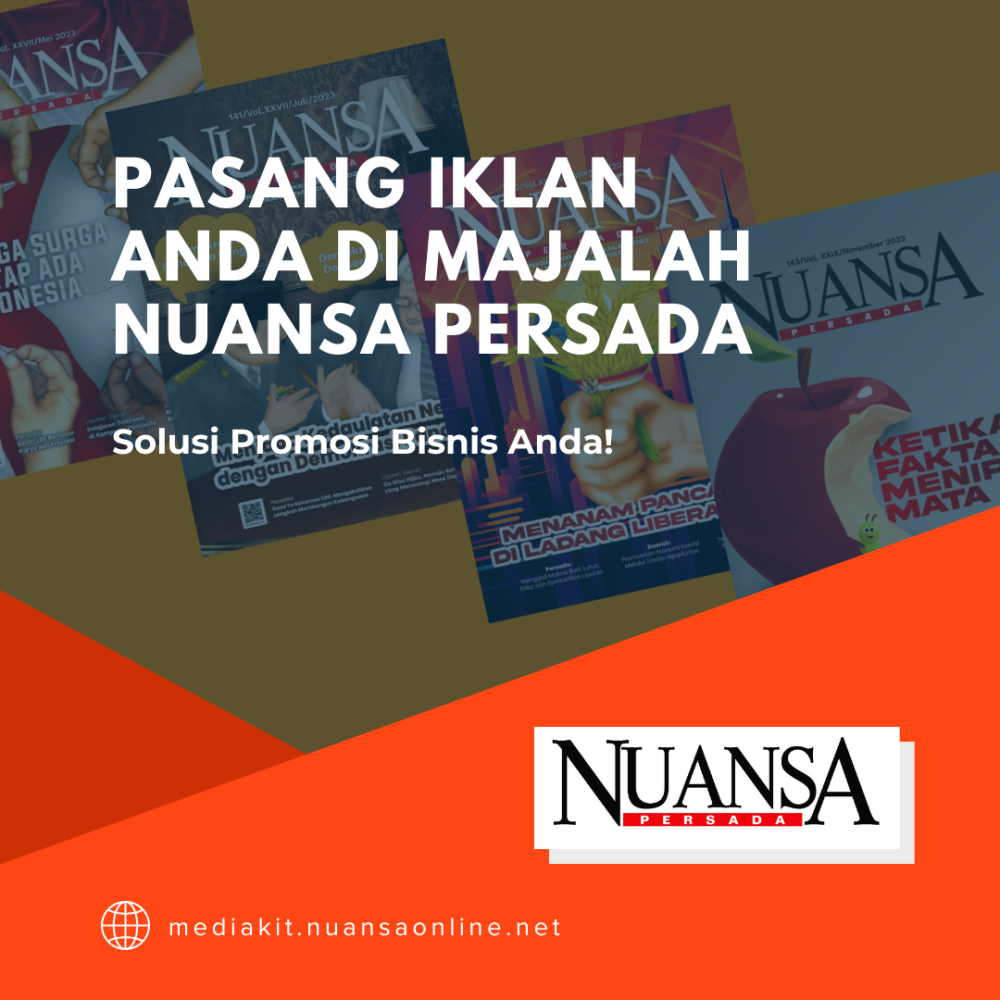












Jangan kita hanya berpikir kita punya uang dan beli bahan makanan
Tetapi seharusnya berpikir bagaimana agar ketercukupan bahan pangan bisa kita siapkan, dan lagi juga harus mampu memenuhi kebutuhan pangan dimasa depan