Oleh: Bambang Supriadi (Biro LISDAL DPW LDII Provinsi NTB)
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, baru-baru ini menerima Anugerah Ekonomi Hijau detikcom atas kiprahnya melindungi lingkungan dari ancaman sampah dan kerusakan ekosistem. Apresiasi ini tentu layak disambut positif, sebab menunjukkan bahwa isu persampahan telah mendapat perhatian serius.
Namun, lebih penting daripada penghargaan adalah memastikan komitmen pemerintah dalam menuntaskan persoalan sampah benar-benar terwujud.
Sejak 2017, pemerintah mencanangkan program ambisius “Indonesia Bersih Sampah 2025”. Target ini dituangkan dalam Perpres 97/2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Sasaran yang ditetapkan cukup jelas, 30 persen pengurangan sampah dan 70 persen penanganan sampah, sehingga total sampah nasional dapat dikelola 100 persen. Hingga 2024, data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat capaian pengelolaan sampah baru 59,74 persen, dengan komposisi pengurangan 13,24 persen dan penanganan 46,51 persen. Artinya, masih ada sekitar 40,26 persen sampah yang sama sekali tidak terkelola. Angka ini menunjukkan betapa besar persoalan yang belum terselesaikan.
Masalahnya bukan hanya pada teknis pengelolaan, tetapi juga pada aspek implementasi kebijakan. Meskipun setiap daerah telah diwajibkan menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada), nyatanya banyak yang tidak melaporkan capaian mereka ke dalam sistem.
Pada 2024, hanya 317 kabupaten/kota yang tercatat melaporkan capaian pengelolaan sampah. Artinya, ada ratusan daerah lain yang belum serius menunaikan kewajiban administrasi sekaligus pengelolaan nyata di lapangan.
Kondisi ini menunjukkan adanya jurang antara kebijakan nasional dengan implementasi di daerah. Akibatnya, target 2025 praktis mustahil tercapai. Kini pemerintah menggeser tenggat waktu menjadi 2029. Namun pertanyaan besar pun muncul, “apakah target ini realistis atau sekadar bentuk penundaan janji lama?”
Indonesia sebenarnya memiliki kerangka hukum persampahan yang cukup tegas. Undang-undang 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP 81/2012 menegaskan kewajiban setiap orang untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Misalnya, Pasal 12 ayat (1) Undang-undang 18/2008 menyebutkan:
“Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.”
Bahkan, larangan dan sanksi juga diatur dengan jelas. Pasal 29 Undang-undang 18/2008 melarang praktik-praktik seperti membuang sampah sembarangan, membakar sampah tidak sesuai ketentuan, hingga open dumping di TPA.
Namun, teori hukum sering kali berbeda jauh dari realitas. Di lapangan, membuang sampah sembarangan dan membakarnya masih dianggap hal biasa. Sanksi jarang diterapkan, bahkan di kota-kota besar sekalipun.
Peraturan daerah yang semestinya menjadi ujung tombak penegakan hukum sering kali mandul. Akibatnya, weak law enforcement menjadi masalah klasik dalam pengelolaan sampah. Tanpa penegakan hukum yang konsisten, masyarakat tidak memiliki insentif untuk berubah. Padahal, aturan yang tegas dan konsisten bisa mendorong kepatuhan, sekaligus menumbuhkan kesadaran kolektif.
Tantangan dan Perubahan
Persoalan sampah di Indonesia bukan hanya tentang timbulan yang kian meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan peningkatan konsumsi. Masalah juga semakin kompleks karena terkait dengan isu global. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara penyumbang terbesar sampah plastik di laut.
Hal ini menimbulkan tekanan internasional, sekaligus ancaman bagi ekosistem laut dan sektor perikanan. Di sisi lain, meningkatnya urbanisasi dan pola konsumsi sekali pakai membuat timbulan sampah terus melonjak.
Jika tidak dikelola dengan baik, persoalan ini tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kesehatan, ekonomi, dan reputasi bangsa. Biaya kesehatan meningkat karena polusi, potensi wisata menurun akibat pantai dan sungai kotor, serta peluang ekonomi dari daur ulang terbuang percuma.
Meski tantangan begitu besar, peluang perbaikan tetap terbuka. Indonesia tidak kekurangan regulasi, lembaga, maupun teknologi. Yang dibutuhkan adalah sinkronisasi, komitmen, dan keberanian untuk menegakkan aturan.
Belajar dari kegagalan target 2025, ada beberapa langkah mendesak yang harus segera dilakukan agar target 2029 tidak bernasib sama, di antaranya:
- Penegakkan hukum dan memperkuat regulasi daerah. Setiap kabupaten/kota wajib memiliki peta jalan persampahan yang jelas, terukur, dan konsisten dievaluasi.
- Prinsip Reduce, Reuse dan Recycle (3R) benar-benar diterapkan dengan mewajibkan pemilahan di sumber. Tanpa budaya memilah sampah sejak dari rumah tangga, sistem pengelolaan akan selalu timpang.
- Mendorong ekonomi sirkular. Industri daur ulang dan pelaku pengolahan sampah perlu mendapat insentif, sementara plastik sekali pakai harus dibatasi secara tegas.
- Mengoptimalkan data SIPSN. Sistem ini harus berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang akurat dan transparan, bukan sekadar formalitas laporan.
- Menggalakkan partisipasi masyarakat. Perubahan perilaku warga adalah kunci utama. Tanpa itu, target nasional hanya akan menjadi angka di atas kertas.
Selain itu, perlu pula dorongan bagi teknologi inovatif dalam pengelolaan sampah, seperti Refuse Derived Fuel (RDF) yang mampu mengonversi sampah menjadi bahan bakar alternatif, PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) yang menghasilkan energi terbarukan, maupun bank sampah digital yang memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
Tak kalah penting, berbagai inovasi berbasis kearifan lokal, seperti budidaya maggot untuk sampah organik, komposting, tasorta dan lain-lain. Pun pola gotong-royong dalam pengelolaan lingkungan, perlu terus diperkuat agar solusi yang lahir benar-benar sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.
Namun, teknologi secanggih apa pun tidak akan berarti banyak jika perilaku dasar masyarakat tidak berubah. Tanpa kesadaran untuk memilah sampah sejak dari rumah, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan mendukung sistem pengelolaan yang ada, maka fasilitas modern hanya akan menjadi monumen tanpa jiwa. Pada akhirnya, transformasi budaya dan gaya hidup adalah fondasi utama dari setiap keberhasilan pengelolaan sampah.
Antara Simbol dan Substansi
Penghargaan yang diterima Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq, memang patut diapresiasi. Ia mencerminkan pengakuan atas upaya yang sedang dijalankan. Namun, penghargaan pada dasarnya hanyalah simbol. Yang lebih penting adalah substansi berupa aksi nyata, konsistensi, serta pengawasan ketat agar kebijakan tidak berhenti di atas kertas.
Target 100 persen sampah terkelola pada tahun 2029 bisa menjadi momentum besar, bahkan tonggak sejarah bagi Indonesia. Tetapi, target ini juga berpotensi menimbulkan kekecewaan baru apabila hanya menjadi penundaan janji lama.
Kepercayaan publik akan terkikis jika tidak ada bukti nyata di lapangan. Sebaliknya, jika dijalankan dengan serius, transparan, dan melibatkan semua pihak, 2029 bisa menandai lahirnya kedaulatan Indonesia dalam mengelola sampahnya sendiri.
Kini pilihan ada di tangan kita bersama: pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, masyarakat, akademisi, hingga media. Sampah adalah urusan kolektif; tidak ada satu pun pihak yang berhak mengabaikannya. Kolaborasi lintas sektor adalah kunci agar visi besar ini tidak kandas di tengah jalan.
Namun pada gelaran Indo Waste & Recycling Expo & Forum Agustus 2025, pemerintah mempertegas langkah-langkah strategis untuk mencapai target tersebut. Beberapa kebijakan penting yang disampaikan meliputi:
- Melarang sistem open dumping di TPA, sebagai upaya mengakhiri praktik lama yang mencemari lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat.
- Mendorong 343 kepala daerah menerapkan sistem controlled landfill, dengan pengawasan ketat serta dukungan teknologi yang memadai.
- Menetapkan kriteria baru Adipura yang melarang keberadaan TPS liar, agar penghargaan lingkungan tidak lagi hanya simbolik, tetapi benar-benar merefleksikan kondisi lapangan.
- Mewajibkan industri melalui Program PROPER untuk mengolah minimal 60 persen sampahnya, sehingga beban pengelolaan tidak sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat.
- Memperkuat penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah, baik melalui sanksi administratif maupun pidana, demi memastikan aturan dijalankan tanpa kompromi.
Kebijakan ini memberi sinyal jelas bahwa pemerintah mulai bergerak dari simbol menuju substansi. Namun, yang akan diuji bukan sekadar komitmen di atas podium, melainkan konsistensi dalam implementasi, ketegasan dalam penegakan hukum, serta keberlanjutan dalam pendanaan dan teknologi.
Tahun 2029 semakin dekat. Apakah akan tercatat sebagai tahun emas kedaulatan sampah Indonesia, atau sekadar menambah daftar target yang meleset? Jawabannya ditentukan oleh kita semua, dengan kerja keras, transparansi, dan keberanian untuk berubah.
Indonesia sudah terlalu lama hidup dalam lingkaran masalah sampah. Regulasi ada, kebijakan ada, program ada, tetapi implementasi lemah. Menunda target dari 2025 ke 2029 memberi kita waktu tambahan, tetapi bukan alasan untuk berleha-leha.
Mari jadikan tahun 2029 bukan sekadar janji, melainkan komitmen nasional yang sungguh-sungguh diwujudkan. Karena pada akhirnya, sampah bukan hanya urusan lingkungan, melainkan cerminan peradaban. Pertanyaannya, “apakah kita bangsa yang sanggup bertanggung jawab atas apa yang kita konsumsi dan hasilkan?” Jawabannya akan tercatat dalam sejarah, bukan melalui kata-kata, melainkan melalui tindakan nyata.


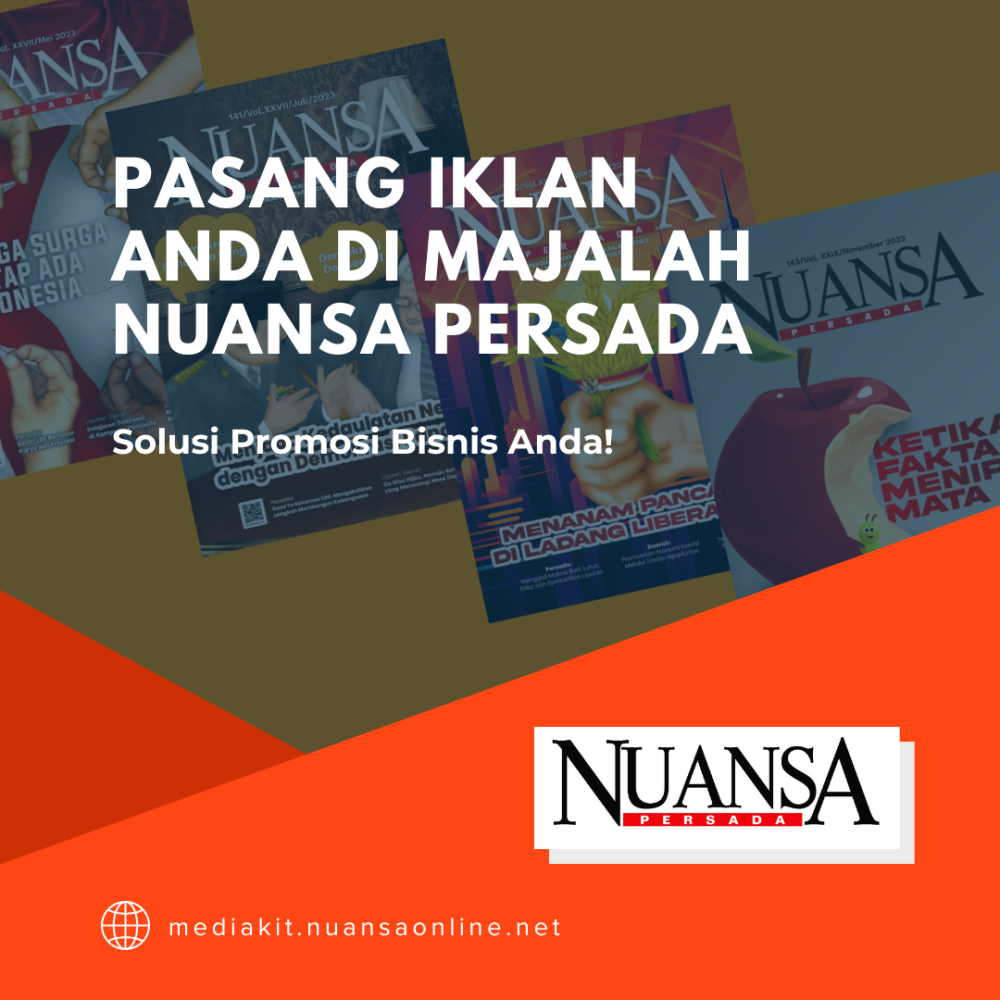












Terima kasih LDII atas artikel Jalan Panjang Indonesia Menuju Sampah Terkelola 100 Persen. Hanya sedikit masukan, penulisan nama penulis sebaiknya diperjelas. Saat ini tertulis ‘Biro LISDAL DPW LDII Provinsi NTB Bambang Supriadi’, sehingga terlihat seolah nama penulis menyatu dengan nama biro. Agar lebih jelas bisa ditulis, misalnya: Oleh: Bambang Supriadi (Biro LISDAL DPW LDII Provinsi NTB). Semoga ke depan semakin rapi, karena artikel ini sangat bagus dan bermanfaat. Terima kasih