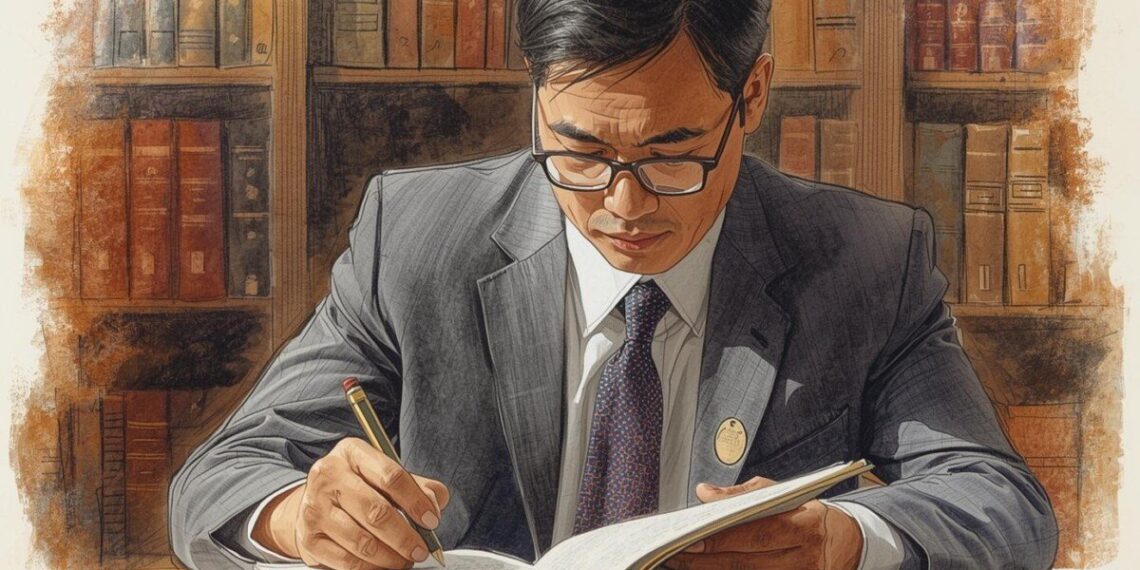oleh Singgih Tri Sulistiyono*
Jika orang berbicara tentang “kedaulatan”, bayangan yang muncul sering berkisar pada kokohnya benteng pertahanan, langkah tegas militer, keluwesan diplomasi, atau kilau kemajuan ekonomi. Itulah narasi yang kerap mengemuka di ruang publik. Sejalan dengan itu, Presiden Prabowo Subianto memberi makna yang lebih tegas dan menyeluruh: kedaulatan bukan sekadar slogan politik, melainkan denyut nadi keberlangsungan bangsa, fondasi kokoh yang menopang langkah Indonesia menuju kemajuan dan martabat di pentas dunia. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus benar-benar berdiri di atas kaki sendiri, menjadikan kedaulatan sebagai sarana untuk meraih keadilan sosial, kemakmuran rakyat, dan kehormatan global, tujuan yang hanya tercapai jika negara mengendalikan penuh sumber daya, kebijakan, dan arah masa depannya. Namun, untuk membangun Indonesia yang maju dan bermartabat seperti itu, baik sekarang maupun di masa mendatang, kedaulatan sebagaimana digambarkan itu belumlah cukup. Dibutuhkan pula “kedaulatan Sejarah”, agar bangsa ini tak hanya berdaulat secara politik dan ekonomi, tetapi juga teguh memegang kendali atas narasi, identitas, dan memori kolektifnya sendiri.
Konsep Kedaulatan Sejarah
“Kedaulatan sejarah” atau yang dapat pula disebut “otonomi sejarah”, adalah saat sebuah bangsa memegang penuh kemudi atas cara ia memahami, menuliskan, dan mewariskan kisah masa lalunya. Ia bukan sekadar deretan peristiwa yang tersimpan di lembar arsip, bukan pula sekadar bab yang dihafal di ruang kelas. Ia adalah napas panjang peradaban, denyut nadi identitas, dan cermin yang memantulkan wajah bangsa sebagaimana adanya dengan segala luka, kebanggaan, dan hikmahnya. Dalam makna yang lebih dalam, kedaulatan sejarah adalah strategi kultural, upaya sadar untuk memastikan bahwa jati diri kolektif tumbuh di atas pondasi pengetahuan yang otentik dan adil. Ia menolak sekadar menjadi gema dari suara asing, yang menuntut agar sejarah disulam dengan benang-benang nilai, kepentingan, dan pandangan bangsa itu sendiri.
Untuk mencapainya, ada dimensi-dimensi yang mesti ditempuh, laksana anak tangga menuju puncak menara ingatan. Dimensi epistemologis yang meneguhkan cara pandang dari akar budaya sendiri; dimensi metodologis yang merangkul semua jejak, dari arsip resmi hingga bisik memori rakyat; dimensi naratif yang memberi ruang bagi semua suara, bukan hanya mereka yang duduk di singgasana; dan dimensi etis-kultural yang menjadikan sejarah cahaya pembebasan, bukan tirai penyesatan. Dengan kedaulatan sejarah, sebuah bangsa bukan hanya menguasai masa lalunya, tetapi juga menyalakan obor yang akan menerangi jalannya menuju masa depan.
Tanpa kedaulatan sejarah, sebuah bangsa berisiko kehilangan kendali atas identitas dan memori kolektifnya, sehingga mudah terjebak dalam narasi yang dibentuk oleh kekuatan eksternal atau kepentingan sempit. Sebaliknya, dengan kedaulatan sejarah, bangsa memiliki kekuatan untuk menentukan arah perjalanan intelektual dan kulturalnya secara berdaulat, sebuah prasyarat esensial bagi tegaknya kedaulatan politik, ekonomi, dan budaya.
Sejarah dan Kuasa: Mengapa Historiografi Tidak Pernah Netral
Sejarah selalu ditulis dari sudut pandang tertentu, dengan kepentingan tertentu. Michel Foucault pernah menyatakan bahwa pengetahuan dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks historiografi kolonial, sejarah diproduksi bukan untuk memahami masyarakat jajahan secara objektif, tetapi untuk membentuk narasi yang mendukung kolonialisme itu sendiri. Sejarah lokal dianggap tidak rasional, tidak sistematis, bahkan dianggap tidak ada. Dengan cara ini, kolonialisme tidak hanya menguasai secara militer dan ekonomi, tetapi juga secara epistemologis.
Historiografi kolonial, sebagaimana tampak dalam karya-karya F.W. Stapel, H. J. de Graaf, ataupun B. Schrieke, pada dasarnya dibangun di atas kerangka epistemologis yang memosisikan masyarakat Nusantara sebagai entitas pasif, statis, dan kurang memiliki dinamika internal yang signifikan. Dalam narasi semacam ini, perkembangan sejarah Nusantara lebih sering digambarkan sebagai respons terhadap intervensi eksternal (India, Timur Tengah, Eropa) daripada sebagai hasil dari proses sosial, politik, ekonomi, dan kultural yang tumbuh dari dalam.
Memang, ada upaya tertentu dari beberapa sejarawan kolonial untuk memberikan ruang bagi peran lokal, misalnya Van Leur yang menekankan pentingnya jaringan perdagangan Asia dan mengakui keberadaan struktur politik dan ekonomi pra-kolonial. Namun, meskipun menawarkan pergeseran perspektif dari historiografi kolonial klasik yang sepenuhnya Eropa-sentris, kerangka berpikir Van Leur tetap beroperasi dalam orbit kolonialisme. Eropa tetap diposisikan sebagai poros penggerak utama sejarah dunia, sementara peran aktor lokal lebih sering dilihat sebagai pelengkap atau sub-narasi dalam kisah besar dominasi Barat.
Dampaknya, historiografi semacam ini membentuk kesadaran sejarah yang timpang: mengabaikan dinamika internal Nusantara seperti persaingan antarkerajaan, inovasi dalam sistem pertanian dan pelayaran, atau transformasi budaya yang muncul dari interaksi antar-etnis di wilayah ini. Lebih jauh lagi, paradigma ini menutup kemungkinan untuk melihat Nusantara sebagai subjek sejarah yang aktif, kreatif, dan memiliki agenda sendiri. Dalam konteks dekolonisasi pengetahuan, warisan cara pandang ini perlu dikritisi dan direvisi, agar sejarah Indonesia dapat ditulis ulang dengan menempatkan pengalaman, logika, dan kepentingan bangsa sendiri sebagai pusat narasi.
Setelah kemerdekaan, muncul upaya untuk menulis ulang sejarah Indonesia melalui Proyek Penulisan Sejarah Nasional Indonesia (terbit pertama kali 1975). Meski proyek ini patut diapresiasi, dalam banyak hal ia masih bersifat negara-sentris, didominasi narasi Jawa, serta terlalu menekankan kontribusi elite dalam perjuangan nasional. Narasi sejarah rakyat, perempuan, daerah, atau kelompok minoritas belum banyak mendapat ruang yang layak. Dengan demikian, kedaulatan sejarah belum sepenuhnya tercapai.
Mengapa Kedaulatan Sejarah Penting bagi Indonesia?
Kedaulatan Sejarah sangat penting bagi Indonesia. Pertama, untuk meneguhkan identitas nasional di tengah arus global. Globalisasi dan revolusi digital menantang identitas nasional, karena narasi global di internet kerap membingkai sejarah Indonesia dari perspektif luar dan mengabaikan pengalaman bangsa non-Eropa. Akibatnya, generasi muda lebih mengenal sejarah Barat daripada perjuangan bangsanya sendiri. Kedaulatan sejarah diperlukan untuk meneguhkan identitas Indonesia yang berakar kuat, berdaulat secara politik, dan merdeka secara budaya.
Kedua, menjawab warisan kolonial dalam pengetahuan. Seperti diketahui bahwa kolonialisme tidak hanya mewariskan ketimpangan ekonomi dan sosial, tetapi juga membentuk cara berpikir, termasuk penggunaan kategori sejarah ala Eropa seperti prasejarah, Hindu-Buddha, Islam, dan kolonial. Kedaulatan sejarah menuntut redefinisi periodisasi, kategori sosial, dan nilai historis dari perspektif bangsa sendiri, agar sejarah menjadi instrumen kesadaran dan emansipasi, bukan sekadar urutan kronologi kekuasaan.
Ketiga, mengembangkan pendidikan sejarah yang membebaskan. Sejarah yang berdaulat akan mendorong transformasi pendidikan sejarah di sekolah. Sejarah tidak lagi diajarkan sebagai hafalan tanggal dan tokoh, melainkan sebagai proses reflektif untuk memahami identitas, mengembangkan empati sosial, dan membentuk orientasi kebangsaan yang kritis. Kurikulum sejarah yang berdaulat memberi ruang bagi narasi lokal, pendekatan multivokal, serta penguatan memori kolektif.
Tantangan dan Jalan ke Depan
Kedaulatan sejarah bukanlah proyek instan, melainkan proses jangka panjang yang memerlukan fondasi kuat. Ia membutuhkan reformasi institusi pendidikan agar pembelajaran sejarah lebih kritis dan relevan, revitalisasi lembaga arsip untuk menjaga dan membuka akses pada sumber-sumber primer, keberanian akademisi keluar dari zona nyaman intelektual, serta kesadaran masyarakat akan pentingnya sejarah bagi identitas dan masa depan bangsa. Tanpa pilar-pilar ini, kedaulatan sejarah akan mudah goyah di tengah arus globalisasi dan banjir informasi.
Namun, jalan menuju kedaulatan sejarah dihadang oleh berbagai tantangan. Politik sejarah kerap memonopoli narasi demi kepentingan kekuasaan, sehingga menghambat multivokalitas dan keberagaman perspektif. Komersialisasi Sejarah menjadikannya sekadar komoditas hiburan yang dangkal, seperti film atau konten media sosial yang mengorbankan validitas akademik demi popularitas. Sementara itu, disinformasi digital melahirkan hoaks sejarah dan narasi menyesatkan yang beredar luas tanpa basis sumber sahih, mengacaukan pemahaman publik.
Menjawab tantangan ini memerlukan strategi nasional yang terpadu. Pertama, penguatan literasi sejarah digital bagi generasi muda agar mampu memilah informasi yang kredibel. Kedua, penulisan ulang sejarah nasional dengan pendekatan Indonesia-sentris untuk menempatkan perspektif bangsa sendiri sebagai pusat narasi. Ketiga, dukungan terhadap riset sejarah berbasis komunitas agar suara dan pengalaman lokal terakomodasi. Keempat, peningkatan kurikulum sejarah yang lebih kritis dan reflektif, mendorong siswa berpikir analitis terhadap masa lalu. Kelima, penguatan posisi sejarawan sebagai penjaga memori kolektif bangsa, sehingga sejarah tidak hanya menjadi milik arsip, tetapi hidup dalam kesadaran publik.
Menulis Sejarah, Menulis Kedaulatan
Kedaulatan sejarah bukan sekadar proyek ilmiah, tetapi sebuah gerakan kebangsaan yang menuntut partisipasi semua elemen masyarakat. Dengan menulis sejarah dari perspektif kita sendiri, dengan suara kita sendiri, dan untuk kepentingan kita sendiri, bangsa Indonesia dapat merebut kembali haknya untuk menentukan narasi masa lalunya, yang sekaligus akan membentuk arah masa depan. Sebagaimana pernah ditegaskan oleh sejarawan Benedetto Croce, “sejarah yang benar adalah sejarah masa kini.” Oleh sebab itu, sejarah Indonesia yang berdaulat adalah sejarah yang ditulis bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tetapi untuk membangun masa depan yang lebih adil, merdeka, dan bermartabat.
*) Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M.Hum adalah Guru Besar Ilmu Sejarah Universitas Diponegoro, sekaligus Ketua DPP LDII dan Ketua DPW LDII Jawa Tengah.