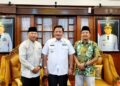Oleh Wilnan Fatahillah*
Wajah Indonesia di pengujung 2025 basah oleh lumpur dan air mata. Banjir besar yang melanda berbagai wilayah di Sumatera dari Aceh hingga Sumatera Barat, dan juga wilayah lain, bukan lagi sekadar fenomena alamiah siklus hujan. Banjir yang menenggelamkan ribuan rumah dan merenggut nyawa adalah manifestasi fisik dari “banjir kezaliman” manusia terhadap alam. Peristiwa itu sebagai akumulasi dari fenomena musibah ekologi seperti: deforestasi hutan tropis di Sumatra dan Kalimantan untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan, penebangan liar, sampah plastik yang mencemari lautan, peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas industri, pembakaran bahan bakar fosil, dan lain-lain.
Krisis perubahan iklim, dan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor, polusi plastik di lautan, perubahan iklim global yang terjadi adalah bentuk pengabaian dan pengingkaran terhadap *ayatullah* yang menunjukkan keajaiban penciptaan Allah SWT, kebesaran Allah dan keteraturan ciptaan-Nya. Keadaan tersebut juga sekaligus sebagai bukti nyata dari yang disebut Al Quran sebagai ”fasad fil ardhi.” Dalam Al Quran, Allah SWT berfirman:
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allâh merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Ar-Rum: 30:41)
Banyak dari kita masih terjebak pada cara pandang antroposentrisme yang sempit, sebuah keyakinan bahwa manusia adalah pusat semesta yang berhak mengeksploitasi alam tanpa batas. Dalam perspektif teologis yang menyimpang, alam dianggap sebagai entitas rendah yang tercipta hanya untuk melayani syahwat ekonomi. Padahal menurut pandangan Islam, manusia berkedudukan sebagai khalifah fil ardh (Wakil Allah SWT di bumi) yang menempatkan manusia pada posisi sentral dalam menjaga dan memelihara alam semesta. Sebagai khalifah, manusia diberi amanah untuk memakmurkan dan memuliakan bumi, bukan merusaknya. Amanah ini datang dengan tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan ekologis dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam bagi semua makhluk.
Namun pada kenyataannya, manusia mengabaikan amanah dan melalaikan kewajiban untuk mengelola dan memelihara bumi dengan baik, adil dan bijaksana. Hal tersebut sebenarnya sudah diprediksi oleh para malaikat ketika diawal penciptaan manusia. Malaikat mengkhawatirkan sifat manusia yang senantiasa membunuh dan merusak. Dalam Al Quran, Allah SWT berfirman:
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۖ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ
Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau? Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (QS. Al Baqarah: 30)
Ayat ini menunjukkan bahwa potensi fasad sejak awal sudah menjadi kekhawatiran di kalangan para malaikat. Namun, Allah SWT memiliki rencana yang lain yakni bahwa akan ada diantara khalifah ini yang akan menjadi para nabi dan rasul, orang-orang sholeh, dan penghuni surga. Ayat ini juga menjadi pelajaran bagi manusia untuk menghindari sifat khianat sebagai wakil Sang Pencipta di muka bumi yang bertugas memakmurkan bumi beserta isinya.
Manusia yang khianat dengan amanah ini dikategorikan sebagai orang munafik yang berusaha merusak di bumi, seperti tanaman dan ternak, padahal Allah SWT tidak menyukai perbuatan kerusakan tersebut, serta mengancam mereka dengan neraka jahannam· Dalam Al Quran, Allah SWT berfirman:
وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ
Artinya: “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan (kerusakan).”. (QS. Baqarah: 205).
Oleh karenanya Allah SWT mengingatkan dan melarang manusia untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Dalam Al Quran, Allah SWT berfirman:
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ
Artinya: ‘Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik’ . (QS. Al-A’raf: 56).
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam secara gamblang menegaskan umat Islam tidak boleh melakukan tindakan yang membahayakan kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain, termasuk merusak lingkungan. Merusak lingkungan berarti membahayakan kehidupan manusia dan makhluk lain.
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ
*Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.* (HR. Ibnu Majah).
Prinsip la dharara wa la dhirar (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain) adalah salah satu hadits nabi yang kemudian menjadi kaidah fikih yang paling fundamental. Dalam ajaran Islam, alam semesta adalah ayatullah al-kawniyyah (tanda-tanda kebesaran Allah) yang memiliki hak hidup dan kesucian. Tauhid tidak hanya mengatur hubungan vertikal manusia dengan Allah SWT tetapi juga hubungan horizontal yang harmonis antara sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Itulah hubungan yang harus dijaga keseimbangannya, termasuk menjaga keseimbangan ekologi. Konsep mizan (keseimbangan atau timbangan) adalah inti dari pemahaman keteraturan ekologis dalam Islam. Dalam Surah Ar-Rahman ayat 7-8, Allah SWT berfirman:
وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
Artinya: ‘Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan.’ (QS. Ar-Rahman: 7).
أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ
Artinya: Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. (QS. Ar-Rahman: 8).
Ayat-ayat ini secara gamblang menyatakan bahwa Allah SWT telah menciptakan langit dan menetapkan mizan atau keseimbangan. Kata mizan di sini memiliki makna yang luas, mencakup keseimbangan fisik, moral, sosial, dan ekologis. Para mufasir, seperti Ibnu Katsir dan Al Qurtubi, menafsirkan mizan dalam ayat ini sebagai keadilan dan keseimbangan dalam segala sesuatu yang diciptakan Allah. Ini berarti bahwa setiap komponen alam semesta memiliki peran dan fungsinya masing-masing yang saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam suatu sistem yang teratur. Gangguan pada satu sistem dapat berdampak pada seluruh sistem, sebagaimana efek domino yang merambat. Manusia mendapatkan tugas untuk menjaga keseimbangan tersebut dan tidak merusaknya.
Kesadaran manusia terhadap pelestarian lingkungan, sudah saatnya selalu dikaitkan dengan keyakinan agama atau tauhid yang merupakan inti dari ajaran agama. Sebagai contoh, upaya menjaga kelestarian alam bukan sekadar tugas saintifik atau politik, melainkan panggilan iman, oleh karenanya merusak alam dianggap sebagai pengingkaran terhadap Allah SWT. Alam semesta disebut sebagai Ayatullah al-Kawniyyah (tanda-tanda kekuasaan Allah yang terhampar), maka setiap kerusakan pada spesies atau ekosistem berarti hilangnya satu tanda kebesaran Allah SWT. Manusia sebagai khalifah (pengelola/penjaga) akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah SWT. Alam semesta tercipta dalam kondisi seimbang, maka kedudukan agama mengajarkan umatnya untuk menjaga keseimbangan dan tidak merusak keseimbangan tersebut demi syahwat ekonomi semata.
Saatnya umat Islam bergerak untuk membumikan ekoteologi sebagai bentuk dakwah amar ma’ruf nahi munkar. Membumikan ekoteologi menuntut kita untuk mengubah orientasi dari ego-sentris menuju eko-sentris. Agama harus hadir di garis depan untuk memberikan label “haram” pada setiap tindakan yang memicu bencana ekologis. Fikih juga tidak hanya sibuk mengurusi ritual dalam sisi privat, tetapi harus hadir dalam sisi ekologi seperti hadirnya rumusan “Fikih Lingkungan” atau Fikh al-bi’ah yang membahas secara detail persoalan konservasi sumber daya alam (air, hutan, dan kawasan lindung), pengelolaan limbah (sampah dan 3R), perubahan iklim dan energi (mitigasi bencana, energi terbarukan, dan emisi karbon), fikih satwa dan biodiversitas, dan fatwa-fatwa lingkungan hidup.
Selain usaha untuk memperdalam kajian ekoteologi di berbagai bidang, hal yang sangat penting untuk segera dilakukan adalah “taubat ekologi”. Keprihatinan atas banjir di Sumatera dan wilayah lainnya tidak cukup hanya dengan mengirimkan bantuan logistik atau membangun posko pengungsian. Itu hanyalah pengobatan atas gejala, bukan penyembuhan atas penyakit. Kita memerlukan “Pertobatan Ekologis” secara kolektif.
Pertama, pemerintah harus berani mengakui kesalahan dalam tata kelola lingkungan alam dan bersedia memperbaikinya serta berani melakukan audit ekologis berbasis keadilan iklim. Setiap kebijakan yang merusak ekosistem harus dihentikan, atas nama keselamatan jiwa (hifzh an-nafs) yang merupakan inti dari tujuan syariat (maqashid syariah).
Kedua, institusi keagamaan harus mengarusutamakan dakwah ekologi. Mimbar-mimbar agama tidak boleh bisu melihat perusakan hutan dan pencemaran sungai. Kita butuh narasi agama yang segar, yang mampu menggerakkan umat untuk melakukan pengurangan plastik, menanam pohon, dan mengelola sampah (zero waste) sebagai wujud nyata dari keimanan.
Ketiga, masyarakat harus menyadari bahwa gaya hidup konsumtif adalah bahan bakar bagi perubahan iklim. Kesederhanaan (zuhd) bukan berarti hidup miskin, melainkan hidup yang sadar akan batas-batas keseimbangan alam.
Banjir di Sumatra adalah pengingatan keras bahwa alam memiliki batas ukuran, ketahanan, dan kesabarannya. Jika kita terus memperlakukan bumi hanya sebagai komoditas, maka bumi akan membalasnya sebagai bencana. Membumikan ekoteologi adalah jalan pulang untuk memulihkan hubungan kita dengan Sang Pencipta melalui pemuliaan terhadap ciptaan-Nya. Sebelum air bah itu benar-benar menenggelamkan peradaban kita, mari kita bangun “Bahtera Nuh” modern bernama kesalehan ekologis.
*) Dr. Wilnan Fatahillah, S.H.I, M.H, M.M, adalah pengurus Departemen Pendidikan Keagamaan dan Dakwah DPP LDII.