Oleh Sudarsono dan Sri Wilarso*
Ketika selesai membahas jejak karbon dan cadangan karbon, tanpa terasa pembicaraan bergeser pada isu perdagangan karbon (carbon trading), katanya merupakan isu yang seksi. Di sisi lain, pernyataan menarik terlontar dari salah satu peserta diskusi yang membuat pembicaraan semakin menghangat. Lontaran pendapatnya yang menghangatkan suhu diskusi.
Katanya, perdagangan karbon itu hanyalah iming-iming (gimmick) saja, sejak pertama diluncurkan sampai dengan sekarang transaksi yang terjadi sangat kecil. Jangan sampai kita mengusung isu yang kurang jelas prospek nya karena perdagangan karbon adalah isu derivatif, yang masih perlu dilihat perkembangannya, tetapi secara historis kurang meyakinkan.
Pernyataan itu, awalnya bukan isu prioritas untuk dikaji, tapi justru memicu keingintahuan untuk menggali lebih dalam tentang perdagangan karbon. Apa benar hanya gimmick saja? Apa ada cerita keberhasilan yang dapat dijadikan sebagai model? Kalaupun gimmick, apa itu di Indonesia saja ataukah global? Inilah hasil pengumpulan informasi terkait perdagangan karbon sebagai bahan untuk menambah wawasan masyarakat dan para pemangku kepentingan.
Apa itu Perdagangan Karbon?
Perdagangan karbon (carbon trading) didefinisikan sebagai suatu mekanisme pasar untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dengan memberi harga pada polusi yang diemisikan ke atmosfer bumi. Sederhana, otoritas pemegang kekuasaan menetapkan batas emisi GRK (atau dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut CAP – dibaca KEP, buka bacaan untuk kata stempel) untuk suatu sektor atau wilayah tertentu, lalu memperjualbelikan izin emisi GRK (allowances) atau kredit hasil pengurangan emisi (offsets) agar entitas pelaku ekonomi dapat memilih opsi pengurangan yang paling murah dan cepat (misalnya, bisa memilih allowances atau offsets).
Di atas kertas, dengan adanya pilihan antara allowances dan offsets tersebut, akan menciptakan ekonomi pasar, yang mendorong inovasi dan efisiensi. Namun dalam praktiknya, berbagai aspek implementasinya (misalnya: desain kebijakan, kualitas pengukuran, tata kelola, dan integritas proyek) akan menjadi penentu apakah perdagangan karbon menghasilkan pengurangan emisi nyata atau sekadar menjadi gimmick reputasional.
Namun demikian, konsensus yang disepakati hingga saat ini menunjukkan bahwa perdagangan karbon itu nyata karena telah beroperasi dalam berbagai skema formal dan pasar sukarela di banyak negara. Namun seberapa nyata atau besar dampaknya, sangat bergantung pada keketatan aturan main, kejujuran cara perhitungan, dan keadilan manfaatnya bagi masyarakat yang terdampak. Pernyataan terakhir ini sejalan dengan apa yang dilansir sebagai kontroversi di awal tulisan ini.
Bagaimana Cara Kerja Perdagangan Karbon?
Terdapat dua cara kerja perdagangan karbon yang sudah berjalan saat ini, yaitu skenario cap-and-trade yang ditujukan untuk compliance market dan skenario offset yang sifatnya sukarela (voluntary) dan merupakan pelengkap dari compliance.
Dalam skenario cap-and-trade, regulator menetapkan total batas emisi (cap), menerbitkan sejumlah izin (allowances), dan mewajibkan setiap entitas atau Perusahaan yang melepaskan GRK menyerahkan allowances sebanyak emisi GRKnya. Dalam skenario ini, Perusahaan yang mampu berhemat emisi GRK akan memiliki allowances berlebih yang bisa dijual, sebaliknya yang boros emisi GRK dan untuk menurunkannya perlu biaya mahal, dapat memilih opsi membeli tambahan allowances. Salah satu kelemahan skenario ini antara lain jika tidak ada sangsi tegas bagi yang melanggar (non-compliance) maka akan menimbulkan melemahnya kepatuhan Perusahaan terhadap batas emisi GRK yang telah ditentukan.
Dalam skenario offset, kredit carbon dihasilkan oleh kegiatan atau proyek yang menghindari, mengurangi, atau menyerap emisi GRK, misalnya konservasi hutan, reforestasi, penangkapan metana, dan efisiensi energi. Karena bersifat sukarela, maka proyek pengurangan emisi GRK tidak akan terjadi tanpa pendanaan karbon, yang merupakan kelemahan dari skenario ini. Biasanya skenario offset digunakan untuk menutup sisa emisi GRK yang sulit dihilangkan, dengan menyalurkan dana ke proyek konservasi atau proyek pengembangan teknologi rendah karbon.
Isu perdagangan karbon menjadi semakin seksi dengan ditandatanganinya Paris Agreement, yang Indonesia ikut menandatangani dokumennya, sehingga berkewajiban untuk memenuhi kesepakatan penurunan emisi karbon yang telah ditentukan besarannya. Keberadaan pasar sukarela juga mengangkat isu perdagangan karbon di Indonesia, meskipun berbagai kendala tetap menjadi potensi masalah yang perlu terus diperbaiki.
Adakah Kontroversi dalam Perdagangan Karbon?
Pro dan kontra dalam perdagangan karbon saat ini masih merupakan keniscayaan, dan para pihak menggunakan argumentasi pembenarannya masing-masing. Bagi yang percaya bahwa perdagangan karbon itu nyata menggunakan agumentasi efisiensi biaya, karena perdagangan karbon memungkinkan target emisi GRK tercapai dengan biaya lebih rendah, harga karbon yang kredibel akan menggeser modal ke teknologi bersih, mengarahkan industri menuju ke efisiensi proses, pemanfaatan bahan baku rendah emisi GRK, dan elektrifikasi.
Bagi yang percaya bahwa perdagangan karbon itu hanya akan menjadi gimmick menggunakan argumentasi kualitas offset lemah jika tanpa dana karbon, kredit tidak mewakili pengurangan nyata, adanya kebocoran cadangan karbon akibat kebakaran hutan dan alih fungsi lahan, adanya fenomenan double counting sehingga pengurangan emisi GRK global menjadi ilusi. Intinya, perdagangan karbon bekerja jika integritasnya tinggi dan kebijakannya ketat; sebaliknya, adanya banyak celah dalam tata kelola membuatnya tampak seperti gimmick.
Success Story di Tingkat Regional dan Global
Berbagai cerita sukses telah terlihat di tingkat regional dan global, terutama di Eropa, Amerika Utara, China dan Asia Timur, Asia Tenggara, Amerika Latin dan Afrika. Di Eropa, penurunan emisi GRK sektor listrik dan industri, pergeseran dari batu bara, dan percepatan penggunaan energi terbarukan, di Amerika Utara – program regional mendanai efisiensi energi, menekan intensitas karbon kelistrikan, dan membiayai adaptasi kebakaran hutan, di Tiongkok dan Asia Timur telah dirumuskan standar MRV nasional, sebagai fondasi pasar terbesar secara volume. Di Asia Tenggara (termasuk Indonesia) telah diinisiasi bursa karbon domestik, kredensial proyek kehutanan/energi, dan peningkatan partisipasi korporasi. Sedangkan di Amerika Latin dan Afrika – implementasi proyek kehutanan berpotensi besar menahan deforestasi dan mendanai penghidupan lokal.
Selain sederet cerita sukses, sejumlah tantangan masih dihadapi dalam perdagangan karbon di tingkat regional dan global dan regional, antara lain perlunya harmonisasi kebijakan antarnegara bagian/provinsi, perlunya menetapkan ambisi cap dan memperluas sektor selain Listrik, dan integritas proyek hutan/peat, hak ulayat, dan pemerataan manfaat, serta risiko kebakaran/EL Niño, tekanan komoditas, dan kapasitas MRV.
Success Story di Indonesia
Indonesia memiliki stok karbon hutan tropis dan gambut yang besar, serta telah membangun infrastruktur pasar karbon domestik. keberadaan bursa domestik, registri nasional untuk unit karbon, dan aturan teknis MRV menyiapkan fondasi pasar karbon yang kuat. Selain itu, Indonesia mempunyai peluang implementasi proyek konservasi, restorasi gambut, energi terbarukan, dan efisiensi industri dapat menghasilkan kredit karbon berkualitas dan menarik pendanaan. Namun demikian, kejelasan hak lahan, pembagian manfaat, dan pengawasan independen menjadi tantangan sebelum Indonesia dapat merealisasikan potensi nilai tambah dari perdagangan karbon. Keberhasilan Indonesia akan ditentukan oleh kualitas standar, konsistensi kebijakan, dan tata kelola yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan.
Kalimantan memiliki beberapa contoh nyata keberhasilan pelaksanaan perdagangan karbon, terutama melalui pendekatan berbasis yurisdiksi dan program kehutanan sosial. Dua kasus yang menonjol dan dapat dijadikan sebagai ceritera keberhasilan perdagangan karbon di Kalimantan, Indonesia antara lain:
1. Program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) di Kalimantan Timur – menjadikan Kalimantan Timur sebagai provinsi pertama di Indonesia yang berhasil menerima pembayaran berbasis kinerja (Result-Based Payment/RBP) dari program FCPF Carbon Fund yang dikelola oleh Bank Dunia. Penurunan emisi yang ditargetkan sebesar 22 juta ton CO₂e selama periode 2019–2024, dengan nilai kompensasi USD 110 juta (setara Rp1.6 triliun), dengan harga USD 5 per ton CO₂e. Pembayaran pertama, sebesar USD 20.9 juta (Rp. 313 miliar) telah diterima dan dialokasikan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Tujuan proyeknya adalah pencegahan deforestasi, degradasi hutan, dan peningkatan tata kelola hutan di tingkat tapak. Dampak sosial program ini berupa pelatihan pendamping lokal, penguatan kapasitas desa, dan pembagian manfaat yang inklusif
2. Perdagangan Karbon Berbasis Komunitas di Desa Laman Satong, Ketapang, Kalimantan Barat – mengelola lebih dari 1,070 ha hutan tropis melalui skema kehutanan sosial dan berhasil menjual kredit karbon ke pasar sukarela internasional. Bermitra dengan GAIA Indonesia sebagai fasilitator dan penghubung ke pembeli karbon. Volume karbon yang diperdagangkan mencapai lebih dari 10,000 ton CO₂e. Pendanaan hasil karbon digunakan untuk reforestasi dan perlindungan keanekaragaman hayati, program pendidikan dan Kesehatan, pembangunan infrastruktur desa, dan akses air bersih dan pengembangan ekonomi lokal. Dampak sosial dan lingkungan berupa masyarakat lokal menjadi pelaku utama konservasi, kredit karbon yang dijual mewakili komitmen nyata terhadap keberlanjutan, dan pembeli karbon mendapat jaminan bahwa kontribusinya berdampak langsung pada pelestarian hutan dan kesejahteraan komunitas
3. Perdagangan Karbon berbasis voluntary dari Perusahaan di Hutan Pendidikan Gunung Walat yang dikelola oleh Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University, sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini menerima pendanaan dari Perusahaan Perusahaan besar seperti PT Tanabe Japan, PT Toso Company, PT NYK Group, PT Conoco Phillips Indonesia. Skema yang digunakan adalah Perusahaan memberikan dana untuk menanam pohon dan memeliharanya. Karbon yang berhasil diserap harus dilaporkan setiap tahun kepada perusahaan sebagai bukti atas kompensasi dana yang telah diberikan.
Ketiga contoh ini mengilustrasikan bahwa perdagangan karbon di Kalimantan dan di Gunung Walat bukan sekadar wacana, melainkan sudah menghasilkan pendanaan nyata, pengurangan emisi terverifikasi, dan manfaat sosial yang terukur. Jika dikelola dengan transparan dan inklusif, skema seperti ini bisa menjadi tulang punggung transisi hijau di tingkat lokal dan nasional.
Penutup
Apakah perdagangan karbon nyata atau hanya iming-iming (gimmick) saja? Kesimpulan singkatnya, perdagangan karbon adalah mekanisme nyata yang sudah berjalan dan mampu menurunkan emisi GRK bila dirancang dan diawasi dengan baik. Namun demikian, perdagangan karbon menjadi gimmick yang too good to be true alias hanya iming-iming saja ketika kualitas kredit karbonnya rendah, penghitungan ganda terjadi, cap yang ditentukan terlalu longgar, dan atau manfaat sosial dari perdagangan karbonnya diabaikan. Dengan kata lain, efektivitas perdagangan karbon bukan soal konsep pasarnya, melainkan kualitas kebijakan, tata kelola, dan integritas pelaksanaannya yang akan menjadi penentu apakah menjadi nyata atau sekedar iming-iming (gimmick) semata.
Perdagangan karbon bukan sekadar slogan. Di banyak wilayah, ia telah menurunkan emisi sektor listrik dan industri, mengarahkan pendapatan publik ke efisiensi energi, dan menyalurkan modal ke konservasi hutan serta teknologi bersih. Namun, diakui atau tidak pasar karbon juga mempunyai kelemahan. Tanpa standar yang ketat, pengawasan yang independen, dan perlindungan sosial, perdagangan karbon bisa berubah menjadi iming-iming (gimmick) yang menutupi kelambanan transformasi sektor riil untuk menurunkan emisi GRK.
Jalan tengah yang perlu difahami adalah memperlakukan perdagangan karbon sebagai alat—bukan tujuan, dan keberhasilannya ditentukan oleh besaran cap yang menurun dan ditegakkan; integritas offset yang dapat diaudit; tata kelola pasar karbon yang transparan dan bebas konflik kepentingan; serta keberpihakan pada keadilan iklim dan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan desain yang baik, perdagangan karbon dapat menjadi bagian inti dari strategi global menahan krisis iklim sambil memastikan transisi yang adil dan efektif.
Mengetahui apa dan bagaimana perdagangan karbon, berarti kita sudah membantu memahami salah satu mekanisme untuk menurunkan GRK dan berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Lembaga Dakwa Islam Indonesia (LDII) sebagai organisasi kemasyarakatan Islam telah berkomitmen untuk berkontribusi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, salah satunya melalui karya dan kontribusi di bidang sumber daya alam dan lingkungan. LDII secara telah aktif melakukan pengukuran cadangan karbon di berbagai Lokasi konservasi, salah satunya di Bumi Perkemahan Cinta Alam Indonesia (CAI), Wonosalam, Jombang, Jawa Timur yang baru saja diselesaikan dan berhasil mendokumentasikan cadangan karbon di Lokasi Bumi Perkemahan CAI Wonosalam sebesar 17,408.33 ton CO2e, di lahan seluas 21.73 ha.
Kegiatan yang telah dilakukan LDII di bidang lingkungan ini sejalan dengan usaha untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goal, SDG), khususnya SDG13 (Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim), dan SDG7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dan SDG12 (Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung Jawab).
Ayo, jadikan Indonesia sebagai penerima keuntungan (benefactor) perdagangan cadangan karbon dunia untuk kesejahteraan warga dan untuk bumi yang berkelanjutan. Salam perdagangan karbon (carbon trading) untuk masa depan yang lebih baik.
**) Prof. Dr. Ir. Sudarsono, M.Sc, adalah Ketua DPP LDII yang juga Guru Besar pada Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.*
*Prof. Dr. Ir. Sri Wilarso Budi R., M.S adalah Ketua Departemen LISDAL DPP LDII yang juga Guru Besar Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor.*


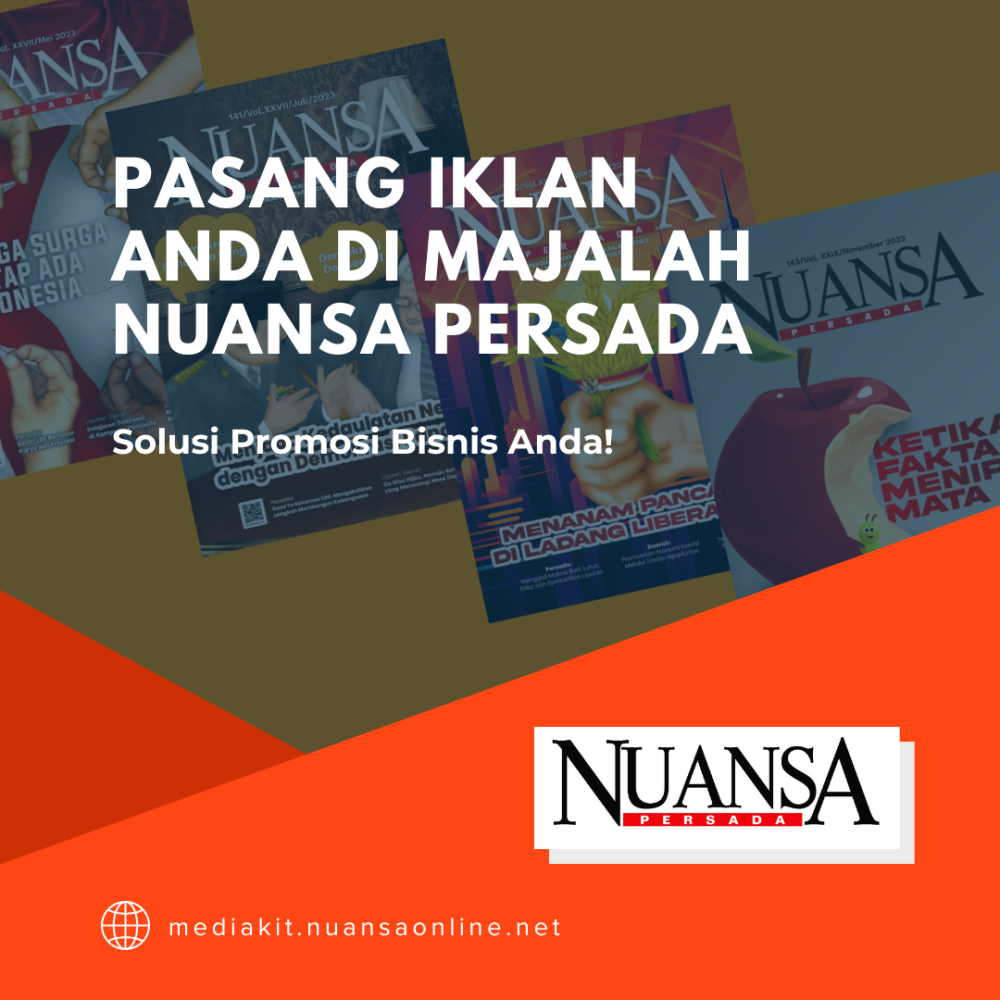










Semoga Allah memberikan kebarokahan