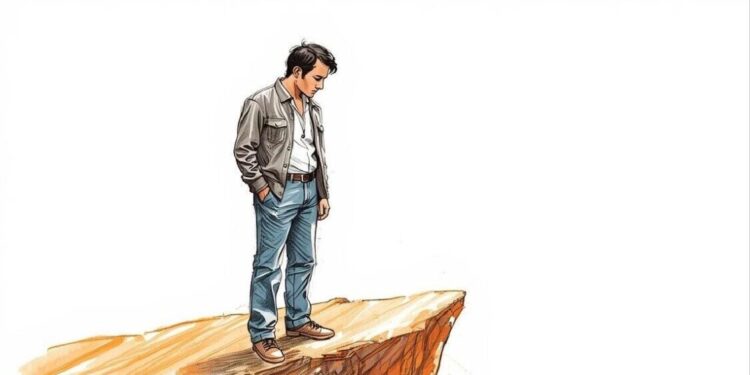Oleh Faidzunal A. Abdillah, Pemerhati sosial dan lingkungan – Warga LDII tinggal di Serpong, Tangerang Selatan
Di dunia yang bising oleh sorakan keberhasilan, gelar panjang di belakang nama, dan sorotan kamera yang memuja popularitas, ada sebuah jalan sunyi yang jarang dilalui: jalan dlosor. Kata sederhana dari lidah Jawa ini mungkin terdengar biasa, tapi maknanya dalam dan menantang zaman. Dlosor secara harfiah berarti menurunkan tubuh ke bumi—duduk di lantai, rebah, menempel pada tanah. Namun, lebih dari sekadar posisi jasmani, dlosor adalah sikap batin: merunduk bukan karena rendah diri, tetapi karena memahami bahwa segala kemuliaan sejati lahir dari kerendahan hati.
Di tengah budaya yang menyanjung kecepatan dan keterlihatan, dlosor menjadi semacam perlawanan halus. Antitesis. Ia menolak gemerlap godaan panggung, menolak sorotan tajam media, dan menolak tepuk tangan riuh. Rasulullah ﷺ sendiri meneguhkan nilai ini dalam sabdanya:
«تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ… طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؛ أَشْعَثُ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٌ قَدَمَاهُ…»
“Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham… Beruntunglah hamba yang memegang tali kendali kudanya di jalan Allah; rambutnya kusut, kakinya berdebu. Jika ia menjaga barisan depan, ia menjaga. Jika berada di belakang, ia tetap setia. Jika meminta izin, ia tak diizinkan; jika memberi pertolongan, pertolongannya tak dihiraukan.” (HR. al-Bukhari)
Hadist ini seolah menampar obsesi manusia modern terhadap popularitas. Rasulullah ﷺ tidak memuji mereka yang dikenal banyak orang, tetapi justru mereka yang tak tercatat, yang mungkin luput dari kamera, yang tersisih di pingiran, namun dekat di mata Tuhan. Hasan al-Bashri pernah mengingatkan, “Seseorang tidak akan mencapai hakikat keikhlasan hingga ia tidak peduli siapa yang memujinya dan siapa yang mencelanya.” Inilah inti dlosor: membebaskan hati dari belenggu pujian maupun cacian, agar amalan tetap murni dan tetap membumi.
Sejarah juga mencatat kisah yang menggugah tentang orang-orang dlosor. Ibn Qutaibah meriwayatkan kisah Shāhibun Naqab —“ Sang Pembuat Lubang.” Ketika pasukan Maslamah bin ‘Abdul Malik mengepung sebuah benteng yang tampak mustahil ditembus, seorang prajurit tanpa nama muncul diam-diam, melubangi dinding pertahanan, dan menjadi jalan kemenangan. Selesai perang, Maslamah mencari siapa pahlawan itu. Namun tak seorang pun muncul. Hingga lewat tengah malam, seorang bertopeng datang menemuinya. Ia berkata: “ Aku adalah orang yang melubangi benteng itu. Tapi ada tiga syarat: jangan tanya namaku, jangan tulis dalam sejarah, jangan beri imbalan apa pun.” Setelah Maslamah menyanggupi, ia pun lenyap kembali dalam kerumunan tentara. Sejak hari itu, Maslamah tidak pernah meninggalkan doa agar Allah menempatkan dirinya bersama Shāhibun Naqab —prajurit bertopeng yang ikhlas dalam kerendahannya. Kisah ini adalah gambaran nyata dari hadis Nabi ﷺ di atas: beruntunglah hamba yang hidup sederhana, yang kakinya berdebu di jalan Allah, yang tak dikenal namanya, tapi tinggi derajatnya di sisi Rabbnya.
Para pemikir dan orang bijak dari berbagai zaman pun menarik kesimpulan yang sama: memuliakan kerendahan hati. Imam al-Ghazali menulis, “Ikhlas adalah ketika amalmu tidak terpengaruh oleh pandangan manusia, baik mereka melihatmu atau tidak.” Syekh Abdul Qadir al-Jailani menasihati, “Jadilah seperti bumi; diinjak setiap makhluk, namun darinya tumbuh segala kebaikan.” Di luar tradisi Islam, kebijaksanaan yang sama pun menggema. Lao Tzu mengingatkan, “Semakin tinggi pohon, semakin dalam akarnya menunduk ke bumi.” C.S. Lewis menegaskan, “Kerendahan hati bukan berarti berpikir kita lebih kecil dari orang lain, melainkan berpikir lebih sedikit tentang diri kita sendiri.” Sementara Rabindranath Tagore menulis, “ Manusia besar adalah ia yang tidak kehilangan hatinya di tengah kebesaran.” Dan Jalaluddin Rumi melengkapinya dengan kelembutan, “Jadilah seperti air. Mengalir ke tempat paling rendah, namun memberi kehidupan bagi segala yang tinggi.”
Di era media sosial, pesan ini terasa semakin relevan. Kita hidup dalam budaya angka—jumlah “like”, pengikut, dan tanda centang biru. Banyak orang tergoda untuk mengejar keterlihatan, seolah nilai diri diukur dari sorotan yang diterima. Dlosor datang sebagai pengingat: tak semua hal mulia harus dipamerkan. Allah sendiri berfirman,
وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
“Barang siapa menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka ia telah berpegang pada tali yang kokoh.” (QS. Luqmān: 22)
Kerendahan hati di hadapan manusia sejatinya adalah ketinggian di hadapan Allah. Jalan dlosor mengajarkan bahwa kemuliaan bukan terletak pada seberapa tinggi kita diangkat orang lain, melainkan seberapa dalam kita mampu menundukkan hati agar amal tetap jernih.
Dlosor bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang menolak dikendalikan ego. Ia adalah seni menahan diri ketika bisa saja kita menuntut pengakuan. Ia adalah kebebasan dari kebutuhan akan sorotan. Sebagaimana bumi yang diam tetapi menopang kehidupan, atau air yang mengalir ke tempat rendah namun menyuburkan yang tinggi. Demikianlah jiwa yang dlosor menyalurkan keberkahan.
Pada akhirnya, bukan nama kita yang akan menembus langit, melainkan amal yang tulus. Bukan gelar yang akan menyelamatkan, melainkan hati yang rela bersembunyi. Juga bukan popularitas yang mengangkat derajat, melainkan kedalaman kita menyelami diri sendiri. Maka, marilah kita belajar dlosor: berbuat tanpa pamrih, merunduk tanpa mengeluh, memberi tanpa menghitung. Sebab kemuliaan sejati bukanlah sorak-sorai manusia, tetapi bisikan lembut dari Yang Maha Tinggi, kala berucap: “Aku ridha padamu.”